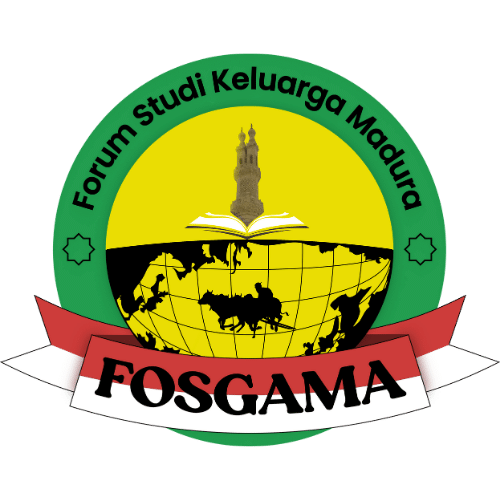Oleh: Saiful Rizal Assalami
Fosgama Mesir – Beberapa bulan lalu, jagat media sosial dikejutkan oleh berita seorang guru yang dipolisikan akibat menegur muridnya. Seperti halnya orang tua, guru di sekolah selain bertugas untuk mengajar, juga memiliki peran yang hampir sama dengan orang tua, yaitu mendidik siswa untuk menjadikan pribadi yang baik. Namun, teguran guru terhadap muridnya acap kali menjadi suatu anomali tersendiri di tengah-tengah masyarakat. Sebut saja Ibu Supriani, guru honorer di Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, yang dipolisikan akibat mendisiplikan muridnya yang nakal.
Teguran dan hukuman seorang guru yang mulanya mempunyai tujuan awal untuk mendisiplinkan, mendidik, dan mengontrol perilaku kurang baik seorang murid menjadi suatu yang pelik untuk diterapkan. Sebab hukuman guru di sekolah menuai pro-kontra lantaran dianggap suatu kekerasan terhadap siswa. Hal ini pada dasarnya bermula dari perbedaan persepsi mengenai cara mendidik anak yang dilakukan oleh orang tua dan guru.
Secara umum, kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik atau mental. Pencegahan ini dikuatkan oleh UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2003 Bab 54, “Guru dan siapa pun lainnya di sekolah dilarang memberikan hukuman fisik kepada anak-anak”. Oleh karena itu, sebagian masyarakat berpendapat bahwa kekerasan dalam dunia pendidikan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan. Namun sebagian yang lain berpendapat, kekerasan yang wajar untuk tujuan mendidik boleh saja dilakukan.
Kekerasan dalam dunia pendidikan memang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan akhir-akhir ini. Kesannya seperti melindungi siswa dari ‘kejahatan’ guru yang bernotabene digaji untuk tugas mencerdaskan dan ‘menyuntikkan’ moral positif kepada siswa. Kendati telah menimbulkan konsekuensi sanksi sosial hingga sanksi hukum, kasus kekerasan yang dilakukan guru kepada siswa, dan orang tua yang juga main hakim sendiri seolah menjadi penyakit yang terus menyebar di pelbagai daerah di Indonesia. Akibatnya, muncul tindakan permisif bahwa guru—selaku pendidik moral—lebih baik melakukan pembiaran ketika siswanya melakukan pelanggaran peraturan di sekolah.
Guru seringkali berada pada posisi yang cukup dilematis, antara kewajiban profesi dan perlakuan masyarakat. Guru dituntut untuk mampu menghantarkan siswa dalam mencapai tujuan pendidikan. Namun, tatkala guru berupaya untuk menegakkan kedisiplinan, guru dihadang oleh UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2003 Bab 54 di muka.
Tidak hanya itu, pendisiplinan yang dilakukan oleh guru sekolah, yang dulunya dianggap biasa-biasa saja, kini malah justru dianggap bertentangan dengan HAM; dalam penandatanganan Konvensi PBB untuk hak-hak anak yang termuat pada Pasal ke-37, “Negara menjamin tidak seorang anak pun boleh mendapatkan siksaan atau kekejaman lainnya.” Pasal ini acap kali dihiperbolis oleh beberapa orang sehingga menjalar pada hukuman dan sanksi yang diberikan oleh guru. Padahal, seorang guru lazimnya pasti memiliki alasan dalam menjatuhkan sanksinya.
Implikasi dari dilema di muka, akhirnya guru menjadi kurang tegas terhadap siswa yang melanggar peraturan dan tata tertib di sekolah. Ketidaktegasan guru berdampak juga terhadap semakin rendahnya wibawa guru dihadapan siswa. Pada dataran berikutnya, guru datang ke sekolah hanya untuk sekadar mengajar, menyampaikan materi sampai habis jam pelajaran dan pulang.
Di lain sisi, hukuman tidak melulu dapat memecahkan masalah, tetapi justru sebaliknya, yaitu dapat menumbuhkan kebencian dan rasa sakit hati siswa. Namun, hukuman bukan berarti harus dihapuskan dari lingkungan sekolah, dan memenjarakan guru yang membuat siswa sakit hati lantaran dihukum atau ditegur. Dengan demikian, teori behaviorisme menurut saya cukup menarik untuk menjadi titik berangkat pembacaan pada fenomena ini.
Prinsip dasar belajar menurut Albert Bandura—salah seorang psikolog aliran behaviorisme—adalah suatu yang dipelajari oleh seorang individu itu sendiri, yang termasuk mengenal pembelajaran sosial dan moral. Bandura menganggap bahwa perilaku seorang siswa dapat dikontrol melalui pemberian hadiah (reward) dan hukuman (punishment), sehingga pendidikan yang diserap tidak hanya teori dan alpa akan nilai dan moral. Karena fungsi utama dari pendidikan adalah sebagai tempat untuk mendidik dan menanamkan nilai-nilai etika, moral, dan akhlak yang baik oleh guru terhadap siswanya.
Hukuman yang dimaksud oleh Bandura tersebut bukan berarti hukuman yang akan berujung pada kekerasan. Tersebab, kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual. Begitu pula hinaan yang meliputi penelantaran dan perlakuan buruk. Oleh karena itu, hukuman yang dimaksud dalam teori ini adalah hukuman yang bersifat mendidik (sesuai kesepakatan guru dan murid) supaya tidak memunculkan kesan negatif.
Dengan demikian, mengontrol murid melalui hadiah dan hukuman dapat pula diartikan sebagai hukum akibat (the law of effect). Hukum ini menghasilkan sebuah teori bahwa satu tindakan yang menghasilkan kesenangan akan cenderung diulangi. Sebaliknya, tindakan yang menghasilkan ketidaksenangan akan cenderung tidak diulangi. Maka dari itu, pemberian hadiah merupakan tindakan yang menyenangkan siswa, sehingga siswa cenderung mau mengulangi untuk melakukan sesuatu yang mendapatkan hadiah tersebut. Sebaliknya, hukuman merupakan tindakan yang tidak menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa cenderung tidak mengulangi sesuatu yang akan mengakibatkan dirinya dihukum.
Teori behaviorisme ini membuat pembelajaran siswa berpusat kepada guru (teacher centered learning), bersifat mekanistik dan berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Teori behaviorisme sangat cocok untuk diterapkan pada siswa yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Dari guru, siswa dapat banyak meniru moral dan hal-hal yang tidak selalu berbentuk materi dan teori, atau bahkan tidak pernah ada dalam buku pelajaran sekolahnya.
Sebagai top figure teladan, guru senantiasa dituntut untuk menyadari dan meresapi pendidikan karakter itu sendiri sebelum menerapkannya kepada anak didiknya. Namun zaman telah berbeda, siswa saat ini dengan siswa zaman guru merasakan pendidikan mengalami perbedaan yang cukup signifikan. Guru saya di Madura yang mengenyam pendidikan di tahun 90-an menceritakan bahwa ia pernah merasakan pendidikan ala tentara. Keras, disiplin, dan tidak mudah menangis hingga mengadu kepada orang tua. Bahkan, ketika siswa mengadu pada orang tuanya karena dicubit atau dihukum oleh guru, sang orang tua malah melengkapinya dengan hukuman-hukuman lainnya, seperti dikurung di kamar selama beberapa hari.
Walakhir, guru tidak selamanya benar dalam memberikan hukuman, kendati tujuannya baik dalam membentuk karakter siswa. Begitu pula dengan siswa, ia tidak melulu harus dilindungi dan dimanja karena ada UU Perlindungan Anak, kendati ia salah dan menelantarkan nilai dan akhlak. Maka dari itu, tidak berlebihan tatkala orang tua yang melaporkan guru yang dianggap melakukan kekerasan kepada anak mereka disebut sebagai bentuk dari arogansi. Pun sangat disayangkan, ketika kasus tersebut harus diselesaikan dan dibawa ke ranah hukum dengan tuntutan penjara dan uang ganti rugi puluhan juta. Tabik!