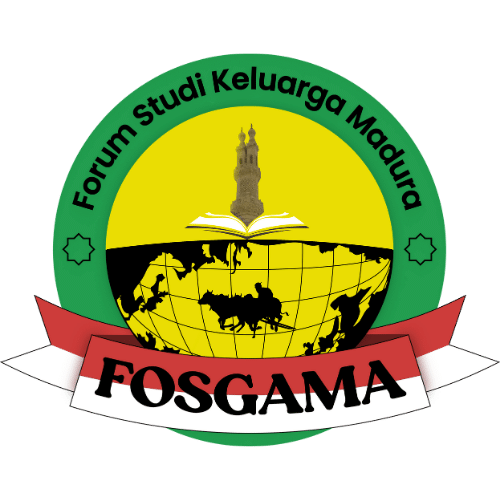Oleh: Muhammad Asrori AS
Fosgama Mesir – Membahas problem suatu komunitas di satu era serta solusi pemecahnya tidak bisa dilepaskan dari unsur keterpengaruhan, dalam arti hubungan dengan keadaan komunitas serupa atau yang lain di waktu yang berbeda. Sebab tidak ada realitas yang muncul begitu saja dari ruang hampa, pasti ada keterkaitan historis secara keilmuan, hukum, politik dan kebudayaan dengan realitas lain.
Tidak hanya yang bersifat problematik, hal yang sama juga berlaku pada peradaban masyarakat Barat yang sekarang menjadi standar kemajuan bagi mayoritas negara-negara dunia di era modern, karena—sekali lagi—realitas Barat ini tidak lain adalah hasil akumulasi perpaduan serapan dari peradaban yang berbeda-beda. Dalam perspektif Dr. Hasan Syafi’i, fondasi terbentuknya Barat modern yang maju adalah telaah terhadap pandangan Filsafat dari Yunani, prinsip-prinsip hukum Romawi, etika dan moral versi Kristen, serta warisan keilmuan Islam.[1]
Poin terakhir menarik untuk disimak, karena selama ini dunia Islam kerap diposisikan berhadap-hadapan dengan term kemajuan, seakan-akan Islam simbol dari dekadensi dan kejumudan. Fakta keadaan rata-rata negara muslim modern memang menjadi dalil kuat akan proposisi tersebut, namun poin utamanya bukan di sana. Apa yang sudah dicapai Barat dengan mengadopsi warisan keilmuan cendekiawan muslim adalah premis minor yang menuntun pada konklusi bahwa capaian serupa bisa diraih oleh dunia Islam, dengan catatan warisan atau turats keilmuan intelektual-intelektual muslim betul-betul dikaji secara komprehensif.
Termasuk di antara turats intelektual muslim yang penting untuk dijadikan sebagai objek kajian adalah kitab-kitab karya Abu al-Walid Ibn Rusyd dari dataran Andalusia. Ulama kelahiran Kordoba pada 520 H. ini memiliki pengaruh besar di balik kemajuan Barat, tulisan-tulisannya menjadi landasan kebangkitan pada era renaisans. Besarnya pengaruh Ibn Rusyd tersebut bukan muncul dari klaim kalangan penulis muslim semata, tetapi juga diafirmasi oleh para cendekiawan Barat dengan dukungan fakta historis.[2]
Oleh karena itu, telaah kitab-kitab Ibn Rusyd menjadi begitu urgen, sebagai batu pijakan dalam upaya mengurai sengkarut problem yang dihadapi dunia Islam dan umat muslim di era modern. Analisis buah pikir ilmuan yang lebih dikenal di dunia Islam lewat perseteruannya dengan Al-Ghazali itu akan merumuskan ide-ide progresif yang dia cetuskan IX abad silam, untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan realitas kiwari yang terjadi di tubuh umat Islam.
Secara umum, karya Ibn Rusyd bisa dikelompokkan menjadi dua. Pertama, komentar dan ringkasan dari turast Aristoteles. Kedua, tulisan mandiri sebagai pemikir, ahli fikih dan filsuf. Kajian yang dimaksudkan untuk mengetahui pemikiran orisinal dia sebagai pemikir—seperti tulisan ini—seyogianya difokuskan pada kategori yang kedua, sebab ada kesulitan untuk memilah antara pendapat dia dan pandangan Aristoteles di kategori pertama, sehingga akan bias.[3]
Kitab-kitab seperti Bidayat al-Mujtahid wa Nihaya al-Muqtashid, Manahij al-Adillah fi ‘Aqaid al-Millah dan Fasl al-Maqol fi ma baina al-Hikmati wa al-Syariati min al-Ittishal termasuk dari kategori kedua yang dimaksud di atas. Pemikiran Ibn Rusyd terjewantahkan secara jelas dalam lembaran karya-karya multidisiplin tersebut. Kemudian secara khusus, nama kitab terakhir akan menjadi objek utama dalam tulisan ini dengan dua alasan. Pertama, karena tidak terikat dengan disiplin ilmu tertentu secara spesifik, berbeda dengan Bidayat al-Mujtahid yang berbicara tentang Fikih saja. Implikasi dari tidak adanya keterkaitan spesifik ini adalah kelenturan aplikasi kaidah-kaidah berpikir yang terdapat di dalam Fasl al-Maqol, baik ke ranah Fikih-Syariat maupun Akidah-Filsafat.
Kedua, konten yang dikandung bersifat global dan tidak terperinci. Beda halnya dengan Manahij al-Adillah sebagai penjelasan lanjutan dari thuruq musytarokah metode dakwah syariat, atau Tahafut al-Tahafut yang memperinci tiga tema utama perdebatan versus al-Ghazali, lebih-lebih risalah Dlamimah al-‘Ilmi al-‘Ilahi yang memperluas perbincangan terkait salah satu dari tiga tema itu, yaitu ilmu Allah Swt.[4]
Telaah kitab Fasl al-Maqol kali ini dilakukan dengan pembacaan primer secara langsung terhadap teks melalui pendekatan deduktif sesuai kaidah ilmu Logika. Selanjutnya rujukan tentang Ibn Rusyd seperti yang terdapat di buku Dr. Murad Wahbah dan Dr. Barakat Duwaidar juga diakomodir sebagai refrensi sekunder. Kemudian untuk menjembatani dengan realitas umat muslim modern, buku-buku Dr. Mahmud Hamdi Zaqzuq dan Dr. Hasan Syafi’i terbilang cukup representatif untuk menjadi rujukan pendukung.
Konten pembahasan pada tulisan ini dibagi menjadi tiga sub tema yang disusun dengan pola piramida, tautan historis dan inklusivisme, kebenaran mutlak, dan elitisme takwil. Secara berurutan ketiga-tiganya berkaitan satu sama lain dan saling melengkapi. Dimulai dari yang cakupannya paling luas dan mendasar selanjutnya ditutup dengan yang bersifat internal bagi umat muslim.
Tautan Historis dan Inklusivisme
Seperti yang sudah disinggung di muka, bahwa tautan historis antar peradaban dalam berbagai aspek adalah sebuah keniscayaan, dan Ibn Rusyd IX abad silam menyadari hal ini dengan baik. Dia menulis: “Ketika berpikir analogis secara Logika sudah dipastikan memiliki konsekuensi hukum wajib seperti halnya berpikir analogis secara Fikih. Apabila masih belum ada seorang pun sebelum kita (sebelum kemunculan Islam) yang merumuskan, maka kita berkewajiban untuk mulai menyusun rumusan konsep dan klasifikasi yang berkaitan dengan pola pikir analogis menurut Logika tersebut. Tetapi sulit atau bahkan mustahil bagi siapa pun untuk memulai semua dari nol.”[5]
Teks ini secara jelas merupakan pengakuan akan adanya unsur keterpengaruhan yang tidak bisa dielakkan. Cendekiawan muslim—dalam konteks objek kitab Fasl-al-Maqol—tidak akan mampu untuk membangun secara mandiri konsep-konsep analogi Logika.
Lebih jauh, afirmasi pasif Ibn Rusyd ini lalu merembet pada sikap aktif dalam menyikapi turats cendekiawan-cendekiawan pra-Islam. Konklusi logis dari premis yang terdapat pada dua baris pertama kutipan di atas adalah keharusan untuk menjadikan warisan keilmuan mereka sebagai rujukan. Dia kemudian menambahkan argumentasi burhan berupa dalil musyahadah dalam teks setelahnya, “Dan semua yang diperlukan dalam hal rumusan analogi-analogi sudah disusun (secara faktual) oleh pemikir-pemikir sebelum kita, maka keharusan kita kemudian adalah menelaah produk pemikiran yang terdapat di kitab-kitab mereka.”[6]
Mengomentari proposisi ini, Dr. Barakat Duwaidar berpandangan bahwa Ibn Rusyd memaksudkannya secara khusus untuk mengonter perkataan al-Ghazali di Tahafut al-Falasifah, berkaitan dengan hukum menelaah turats pra-Islam yang kerap dijadikan tameng oleh golongan yang mengharamkan. Penyimpangan dalam hal pemikiran keagamaan yang sering muncul dari peneliti turats tokoh-tokoh pra-Islam seperti Aristoteles menjadi landasan utama.
Padahal cara berpikir demikian tidak tepat, justru di sini terjadi logical fallacy sejak tataran deskriptif, karena hal ekstrinsik dianggap esensial. Ibn Rusyd mengumpamakan kekacauan logika ini dengan larangan mengonsumsi air karena ada insiden orang mati tersedak saat minum. Kemudian yang dihasilkan bukan maslahat, tetapi mudarat besar. Sebab tersedak bersifat insidental, sedangkan mati karena tidak minum adalah hal yang pasti.[7]
Pada tahap selanjutnya, keniscayaan akan tautan historis ini menuntut keterbukaan pandangan atau inklusif. Metodologi apa pun dan dari siapa pun, selama sama-sama memandu pada cara berpikir yang benar, ia akan diterima dan diakui sebagai jalan kebenaran. Penerimaan yang dimaksud bukan hanya secara akal logis, tetapi juga legal formal syariat, tidak menjadi soal apa keyakinan teologis yang dianut oleh pencetusnya.
Dalam Fasl al-Maqol, Ibn Rusyd ketika mengajukan argumentasi pada keharusan sikap inklusif, premis dan istilah yang digunakan bercorak Fikih, untuk menunjukkan pada penerimaan secara syariah. Dia mengatakan: “. . . karena kebolehan alat yang digunakan untuk menyembelih dalam proses penyembelihan itu tidak mempertimbangkan apakah alat tersebut milik orang yang seagama dengan kita atau tidak. Selama memenuhi syarat (maka sah sembelihannya).”[8]
Implikasi penerimaan secara legal formal syariat ini tidak sederhana. Metodologi berpikir yang diadopsi lalu memiliki kedudukan setara dengan metodologi khas yang biasa digunakan untuk menelurkan produk hukum syariat seperti ilmu Ushul Fikih. Misal ambil nalar berpikir burhani falsafi hasil serapan dari turats klasik pra-Islam sebagai contoh. Nalar burhani falsafi perlu diposisikan sama persis secara hierarki dengan minhaj Ushul Fikih dalam berinteraksi dengan nas-nas keagamaan.
Jika terdapat nas yang tampak lahir sejalan ketika menyinggung topik yang sama, maka tugas nalar burhani falsafi dan Ushul Fikih adalah membahasakan sesuai bahasa masing-masing. Berbeda jika lahirnya nas tersebut seperti bertentangan dengan hasil penalaran keduanya, maka dalam situasi ini yang harus ditempuh adalah upaya takwil. Apabila tidak ada nas sama sekali, nalar burhani falsafi mempunyai ruang untuk berkreasi sebagaimana Ushul Fikih melakukan dengan metode qiyas ushuli.
Pandangan inklusif ini perlu untuk didengungkan di era modern, karena disadari atau tidak, ekslusivisme sebagai antitesa berada di balik tumpukan faktor-faktor yang melatarbelakangi realitas umat muslim sekarang. Dikotomi metodologi antara “islami” dan “nonislami” serta anggapan bahwa bangunan keilmuan Islam sudah final; tidak memerlukan lagi tawaran baru, merupakan salah satu ciri pandangan eksklusif yang sudah sepantasnya dihilangkan. Tidak heran bila Dr. Hamdi Zaqzuq bolak-balik menyebut keharusan untuk menampilkan sikap inklusif dalam berinteraksi dengan peradaban yang memiliki bangunan keilmuan berbeda. Menurutnya, inklusif termasuk dari syarat-syarat yang mutlak harus dimiliki umat muslim jika ingin keluar dari ketertinggalan mereka sekarang.[9]
Sikap inklusif yang dimaksud tidak terbatas pada satu disiplin keilmuan seperti Filsafat saja. Penerimaan tawaran konsep dan metodologi yang berhubungan dengan bangunan minhaj hukum Islam dan pembacaan sejarah juga termasuk dalam aplikasi sikap ini. Seperti disinggung di atas, pada fase selanjutnya serapan ide baru tersebut berhak diposisikan sejajar dengan konsep dan metodologi sebelumnya yang sudah mapan.
Kebenaran Mutlak
Keterbukaan sikap dan pandangan tidak berarti menafikan kebenaran mutlak. Khusus dalam proposisi ini, teks-teks Ibn Rusyd di Fasl al-Maqol memang cenderung disalahartikan, sehingga banyak yang berpandangan bahwa dia berpendapat tidak ada kebenaran mutlak. Dalam konteks penggunaan nalar burhani falsafi, takwil terhadap nas keagamaan bagi dia adalah kebenaran hakiki, karena landasan yang digunakan burhani falsafi pasti berupa premis yang benar secara hakikat, dan nas yang ditakwil memiliki kandungan kebenaran hakiki pula. Satu-satunya yang bisa membatalkan konklusi hasil takwil burhani falsafi ini dalam aspek syariah adalah konsensus.[10]
Sedangkan konsensus dalam hal teoritis yang menjadi objek burhani falsafi menurut pendapat dia tidak mungkin terjadi, pasti ada perbedaan perspektif. Dia menulis: “. . .maka dari itu, Abu Hamid (al-Ghazali) dan Abu al-Ma’ali (al-Juwaini) mengatakan tidak boleh menghukumi kafir orang yang memiliki pandangan berbeda ketika menakwil hal yang (sepertinya) sudah disepakati. Dan (argumentasi-argumentasi itu) menunjukkan pada ketiadaan konsensus yang pasti terkait perkara-perkara teoritis, seperti halnya yang terjadi pada ranah hukum implementatif (Fikih).”[11]
Kebenaran hakiki takwil dan ketiadaan konsensus terkait hal-hal teoritis ini meniscayakan relativitas kebenaran. Mereka yang berbeda ketika menakwil nas keagamaan sama-sama memiliki kebenaran mutlak—terkait makna nas—sesuai hasil penalaran burhani falsafi yang dilakukan, dan tidak boleh disalahkan dengan alasan ada konsensus. Dengan pola yang mirip, Dr. Murad Wahbah mempunyai pemahaman serupa terkait teks-teks Ibn Rusyd di atas meski dengan beberapa perbedaan.
Padahal Ibn Rusyd tidak berpendapat demikian. Dia masih mengatakan dengan jelas adanya nas-nas keagamaan yang tidak boleh diutak-atik dengan alasan takwil. Upaya untuk menyematkan makna lain pada nas sejenis ini dengan cara takwil bisa dipastikan salah, dan dalam term agama divonis kafir. Karena upaya demikian pasti salah secara nalar burhani falsafi dan merupakan bentuk pengingkaran terhadap kebenaran hakiki yang dikandung oleh nas, sedangkan dua hal ini tidak akan pernah bertentangan.
Dia mengatakan: “. . .Dan metode syariat (nas) terbagi menjadi empat. Pertama, bisa dipahami oleh semua golongan (burhani, jadali dan khatabi) dan dipastikan kebenarannya secara deskriptif maupun argumentatif, meskipun narasi yang digunakan khatabi dan jadali (bukan burhani yang pasti benar) dan nas-nas semacam ini tidak boleh ditakwil. Sebab orang yang mengingkari atau menakwil dihukumi kafir”.[12]
Keyakinan terhadap adanya kebenaran mutlak ini yang membuat dia tidak mengadopsi begitu saja semua muatan turats pra-Islam yang dia kaji. Ada standar umum yang menjadi garis pembatas mana yang boleh diserap dan mana yang tidak. Selanjutnya dia menulis: “. . .kita wajib mengkaji perkataan yang terdapat di buku-buku mereka. Jika ada yang selaras dengan kebenaran hakiki, kita terima dan berterima kasih. Apabila tidak sesuai dengan kebenaran hakiki, kita beri catatan dan melarang orang-orang untuk mengikutinya, sembari memaklumi kesalahan yang mereka lakukan.”[13] Pandangan inklusif yang disertai pengakuan kebenaran mutlak seperti ini membuat Ibn Rusyd luwes dengan tetap memiliki jati diri tegas pada saat yang bersamaan.
Ketegasan jadi diri penting untuk dimiliki umat muslim modern, sehingga usaha untuk mengadopsi tawaran-tawaran baru tidak berbalik menjadi senjata yang digunakan menyerang prinsip-prinsip baku yang sudah paten. Dr. Hasan Syafi’i menyinggung fenomena maraknya reinterpretasi di banyak negara-negara Islam, yang justru membahayakan eksistensi Islam dan umat muslim sendiri. Sebab upaya reinterpretasi yang dimaksud berdampak pada tercerabutnya umat muslim dari jati diri mereka, karena akan membongkar asas fundamental yang menjadi tiang penopang.[14]
Namun sering kali garis batas ini dituduh sebagai simbol eksklusivisme. Terbuka kepada tawaran-tawaran baru sembari memegang teguh prinsip dasar disebut sama saja dengan tertutup dan kaku. Padahal sebaliknya, ketegasan jati diri adalah bukti objektivitas ilmiah. Tidak menerima serampangan dan tidak menolak begitu saja konsep yang ditawarkan hanya karena bersumber dari orang yang tidak seagama. Semua ditundukkan pada standar-standar asasi yang ada. [15] Secara logis, ketiadaan asas fundamental di suatu komunitas pada akhirnya hanya akan memutus tautan historis yang disebut di sub bab pertama, bukan saja dengan komunitas yang berbeda, tetapi juga internal komunitas itu sendiri.
Elitisme Takwil
Klaim kebenaran harus diakui menjadi salah satu sumber utama perpecahan kelompok di tubuh umat Islam. Sejak dari kurun abad pertama pasca masa kenabian, perpecahan kelompok menjadi warna yang sangat kentara dalam bentang sejarah perjalanan peradaban Islam. Lebih dari puluhan kali, perpecahan ini menjurus pada peperangan yang menumpahkan banyak darah di tengah-tengah umat muslim.
Bagi Ibn Rusyd, sumber dari perpecahan umat muslim menjadi banyak kelompok ada pada perbedaan takwil nas-nas keagamaan, dan penyebarannya kepada mereka yang masih belum mampu untuk mencerna produk takwil nas dengan baik. Dia mengatakan:
“Maka sudah jelas dari dalil-dalil itu, bahwa takwil yang benar (sekalipun) tidak wajib untuk dicantumkan di kitab-kitab yang biasa dibaca khalayak umum, apalagi takwil-takwil yang salah . . . Dan dari perbedaan takwil serta dugaan wajibnya menyebarkan hasil dari takwil itu untuk kalangan luas, muncullah sekte-sekte yang saling mengkafirkan. . . Mereka (ulama yang menulis hasil takwil nas di kitab yang bisa dikonsumsi secara umum) kemudian membuat orang-orang saling membenci dan berperang satu sama lain.”[16]
Solusi untuk meredam perpecahan umat dari teks ini adalah elitisme takwil. Hasil dari penalaran takwil burhani falsafi terhadap nas harus dikonsumsi secara terbatas, dan ditulis di kitab-kitab yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memahami nalar burhani falsafi. Ibn Rusyd kemudian mengkritik al-Ghazali yang banyak mencantumkan produk takwil di kitab-kitab yang ditujukan untuk kalangan luas, karena apa yang dilakukan al-Ghazali bagi Ibn Rusyd berbahaya pada agama dan nalar falsafi sekaligus. Tidak heran bila muncul banyak kalangan yang mencela Filsafat setelah membaca karya-karya al-Ghazali.[17]
Dampak dari elitisme takwil ini adalah tercapainya tujuan utama syariat, yaitu kondusifitas masyarakat tanpa harus ada friksi di internal umat Islam. Karena mayoritas mereka yang tidak mampu berpikir melalui nalar burhani falsafi, tidak dipaksa masuk ke pola yang berada di luar jangkauan mereka, sehingga fokus untuk meyakini hal-hal prinsipil dan amali yang menjadi kesepakatan bersama, tanpa ribut berdebat masalah-masalah yang membingungkan.
Ibn Rusyd melanjutkan, capaian gemilang di masa awal kemunculan Islam diraih dengan yang sama, yaitu menonjolkan thuruq musytarokah yang mudah dipahami semua kalangan. Kalaupun ada pada masa itu yang melakukan takwil, dia tidak mempublikasikannya secara luas. Situasi yang berbeda terjadi pada masa-masa setelahnya, tak pelak perbedaan dan perpecahan pun mulai menjamur dan menjadi benalu.[18]
Proposisi ini diamini oleh Dr. Hamdi Zaqzuq, khususnya dalam konteks taqrib baina almadzahib guna mengurai benang kusut perpecahan kelompok di tubuh umat muslim. Dia memposisikan diskusi antar kelompok sebagai tahap pertama dari proposal taqrib, dan termasuk dari strategi diskusi yang disebutkan adalah hiwar ‘ala al-qawasim al-musytarokah atau diskusi terkait prinsip-prinsip yang disepakati. Rincian dari prinsip-prinsip ini adalah iman kepada Allah Swt., hari akhir dan berbuat baik.[19]
Maka selama masing-masing kelompok masih meyakini prinsip yang sama, tidak perlu ada gesekan dan permusuhan. Adapun detail dari turunan tiga prinsip tadi, seperti penjelasan sifat-sifat Allah Swt, hakikat kebangkitan di hari akhir kelak dan asal mula penciptaan alam sudah bukan wilayah jumhur. Perdebatan tentang detail-detail semacam ini masuk pada ranah takwil yang hanya bisa dan boleh dilakukan kalangan tertentu.
Dampak lain dari elitisme takwil adalah standardisasi, tidak bisa sembarang orang melakukannya. Kelompok umat muslim yang tidak mampu menjangkau nalar burhani falsafi dengan baik tidak diperbolehkan untuk masuk jauh ke ranah takwil, dan termasuk diantara bagian kelompok ini Hanabilah yang banyak terwakilkan dengan pandangan-pandangan Salafi modern.
Ibn Rusyd memang memperhitungkan Hanabilah dalam lingkaran perbedaan pendapat terkait ayat-ayat mutasyabihat dalam Alquran.[20] Sehingga meskipun pendapat mereka berbeda dengan kesepakatan ahli takwil untuk menakwil mutasyabihat, tetap saja muktabar dan tidak membuat kafir atau sesat, karena timbul dari ketidaktahuan mereka. Dia menulis: “. . . dan takwil selain ahli burhan terhadap jenis nas ini bisa berkonsekuensi kafir atau sesat. Dan di antara nas-nas ini yaitu ayat istiwa’ dan Hadis nuzul . . . Karena terdapat golongan yang tidak mampu berargumentasi kecuali dengan bertendensi pada imajinasi. . . Sulit bagi mereka untuk membenarkan adanya entitas yang tidak bisa diimajinasikan.”[21]
Tetapi dengan catatan, penerimaan bentuk lahir mutasyabihat yang mereka yakini tidak lebih dari apa yang yang dilakukan budak perempuan dalam Hadis jariyah. Apabila masuk pada detail penjelasan dari makna ayat tersebut, maka sudah memiliki konsekuensi serius, karena bukan domain mereka untuk menjelaskan.
Standardisasi ini penting untuk dibakukan dan menjadi pembatas bagi muslim modern, untuk memastikan bahwa yang berpendapat benar-benar yang berkompeten. Tidak hanya dalam ranah teologis dan falsafi yang teoritis, tetapi juga hukum Fikih yang aplikatif. Dr. Hasan Syafi‟i mengungkapkan kegelisahannya terhadap kemunculan banyak orang yang menyeru pada ijtihad dan mendaku mampu untuk berijtihad, padahal sama sekali tidak memiliki kompetensi yang cukup untuk masuk ke dalam ruang itu.[22]
Pengaruh buruk yang ditimbulkan dari keberanian kelompok yang tidak memiliki kualifikasi intelektual ini sama besarnya dengan yang ditimbulkan ahli takwil di atas. Kedua-duanya sama-sama hanya akan mencoreng agama dan menimbulkan perpecahan di tengah-tengah umat Islam yang seharusnya tidak perlu terjadi dan terlalu banyak menguras energi.
Terakhir, kontekstualisasi pemikiran Ibn Rusyd di atas mungkin memiliki banyak kesamaan substansial dengan beberapa ulama klasik lain, bahkan sudah dialih bahasakan oleh banyak pemikir modern dengan bangunan yang lebih sistematis. Namun hal yang terpenting, bagaimana minhaj pemikir Andalusia ini dalam menyikapi fenomena yang terjadi pada umat Islam di zamannya bisa diserap dengan baik.
Buku-buku hasil pemikirannya dan Fasl al-Maqol secara khusus tidaklah lahir dari ruang hampa, ada realitas di tengah-tengah umat Islam yang menuntut dia untuk merespon dan bersikap. Dan jika diperhatikan, keadaan pada masa Ibn Rusyd tidak jauh berbeda dengan yang ada di era modern sekarang, sehingga cara penyelesaiannya juga mirip. Dengan alasan ini, tidak heran bila Dr. Hamdi Zaqzuq sering menyitir kutipan dari kitab Fasl al-Maqol dalam banyak tempat, begitu pula Dr. Hasan Syafi’i ketika membahas konsep pembaharuan.
Spirit menyerap minhaj Ibn Rusyd sukses membuat Barat bangkit dan maju seperti sekarang. Tentu dalam konklusi, pasti terdapat banyak perbedaan antara para pengagum yang tergabung dalam madzhab Rusydiyah Latiniyah dengan Ibn Rusyd sendiri, karena keduanya berbeda sedari prinsip awal. Tetapi bisa dipastikan cara berpikir yang mereka anut sama persis dengan cara berpikir Ibn Rusyd.
Spirit dan hasil yang sama bisa juga didapatkan umat muslim dengan mengkaji turats tokoh multidisplin ini. Piramida tautan historis dan inklusivisme, kebenaran mutlak dan elitisme takwil merupakan iktiar untuk menghadirkan pokok-pokok ide Ibn Rusyd dalam format metodologis yang bisa menyentuh—atau setidaknya mendekati—inti permasalahan yang dihadapi umat muslim, sehingga bisa relevan sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dimaksud.
Sekian.
Daftar Pustaka
Duwaidar, Barakat Abd al-Fattah, Ibnu Rusyd; Manhajuhu wa ‘Aqidatuhu, {Majma‟ Mathobi‟ alAzhar as-Syarif, 2023}
Rusyd, Abu al-Walid bin, Fasl al-Maqol fi ma baina al-Hikmati wa as-Syariati min al-Ittishal, {Kairo, al-Haiah al-Misriyah al-„Ammah li al-Kitab, 2018}
——–, ——-, {Beirut, Markaz Dirasat al-Wahdah al-„Arabiyah, 1997}
——–, ——-, {Dar al-Ma‟arif}
Syafi‟i, Hasan, Qoul fi at-Tajdid, {Kairo, Dar al-Quds al-„Arabi, 2019}
Wahbah, Murad, Madkhal ila at-Tanwir, {Kairo, Dar al-„Alam at-Tsalist, 1994}
Zaqzuq, Mahmud Hamdi, al-Fikru ad-Dini wa Qadlaya al-‘Asr. {1441 H}
——–, al-Muslimun fi Muftariqi at-Thuruq, {Mathobi‟ Dar al-Jumhuriyyah li as-Shohafah, 2021}
Catatan Akhir
[1] Hasan Syafi‟i, Qoul fi at-Tajdid, Dar al-Quds al-„Arabi, Kairo, cet.IV, 2019, hal. 61
[2] Murad Wahbah, Madkhal ila at-Tanwir, Dar al-„Alam at-Tsalist, Kairo, cet I, 1994, hal. 132-135.
[3] Barakat Abd al-Fattah Duwaidar, Ibnu Rusyd; Manhajuhu wa ‘Aqidatuhu, Majma‟ Mathobi‟ al-Azhar asSyarif, cet I, 2023, hal. 61-62
[4] Ketiga-tiganya sudah disinggung oleh Ibn Rusyd di dalam Fasl al-Maqol meski dengan porsi terbatas. Singgungan ini membuat Fasl al-Maqol ibarat pintu masuk atau kitab induk dari yang lain. Lihat lebih lanjut pengantar Muhammad Imarah pada Fasl al-Maqol terbitan Dar al-Ma‟arif, Kairo, cet. III, hal. 8. Baca juga pengantar Muhammad „Abid al-Jabiri di terbitan Markaz Dirasat al-Wahdah al-„Arabiyah, Beirut, cet. I, 1997, hal. 53.
[5] Abu al-Walid bin Rusyd, Fasl al-Maqol, al-Haiah al-Misriyah al-„Ammah li al-Kitab, Kairo, cet. I, 2018, hal. 36
[6] Ibid 7
Barakat Abd al-Fattah Duwaidar, op.cit.,hal. 115-116
[7] Abu al-Walid bin Rusyd, op.cit., hal. 39
[8] Ibid, hal. 36 10
Ibid, hal. 40-41. Proposisi-proposisi seperti detail kebangkitan di hari kiamat dan kekadiman alam adalah produk dari takwil nalar burhani falsafi. Sedangkan penjelasan lanjut dari hakikat ruh merupakan hasil kreasi yang disebut di poin terakhir.
[9] Mahmud Hamdi Zaqzuq, al-Fikru ad-Dini wa Qadlaya al-‘Asr, hal. 125-127
[10] Abu al-Walid bin Rusyd, op.cit., hal 42 dan 45
[11] Ibid, hal. 43 14
Bedanya Dr. Murad Wahbah menggunakan teks-teks di atas untuk membenarkan proposisi klasifikasi kebenaran Ibn Rusyd versi Rusydiyah Latiniyah Barat. Jadi kebenaran versi kelompok pengagum Ibn Rusyd ini ada dua. Pertama, kebenaran dalam perspektif akal dan Filsafat. Kedua, kebenaran dalam perspektif agama dan iman. Lihat Murad Wahbah, op.cit., hal. 135-137.
[12] Abu al-Walid bin Rusyd, op.cit., hal 58
[13] Ibid, hal 38
[14] Hasan Syafi‟i, op.cit., hal 145-147
[15] Hamdi Zaqzuq, op.cit., hal 75-78
[16] Abu al-Walid bin Rusyd, op.cit., hal 62-63
[17] Ibid, hal 54
[18] Ibid, hal 64
[19] Hamdi Zaqzuq, al-Muslimun fi Muftariqi at-Thuruq, hal. 92-94
[20] Abu al-Walid bin Rusyd, op.cit., hal 42
[21] Ibid, 52-53
[22] Hasan Syafi‟i, op.cit. hal 33