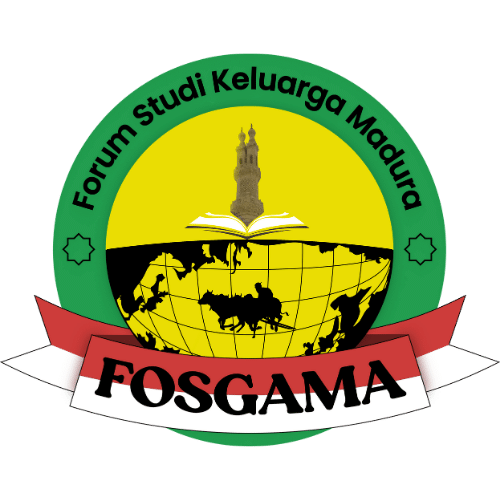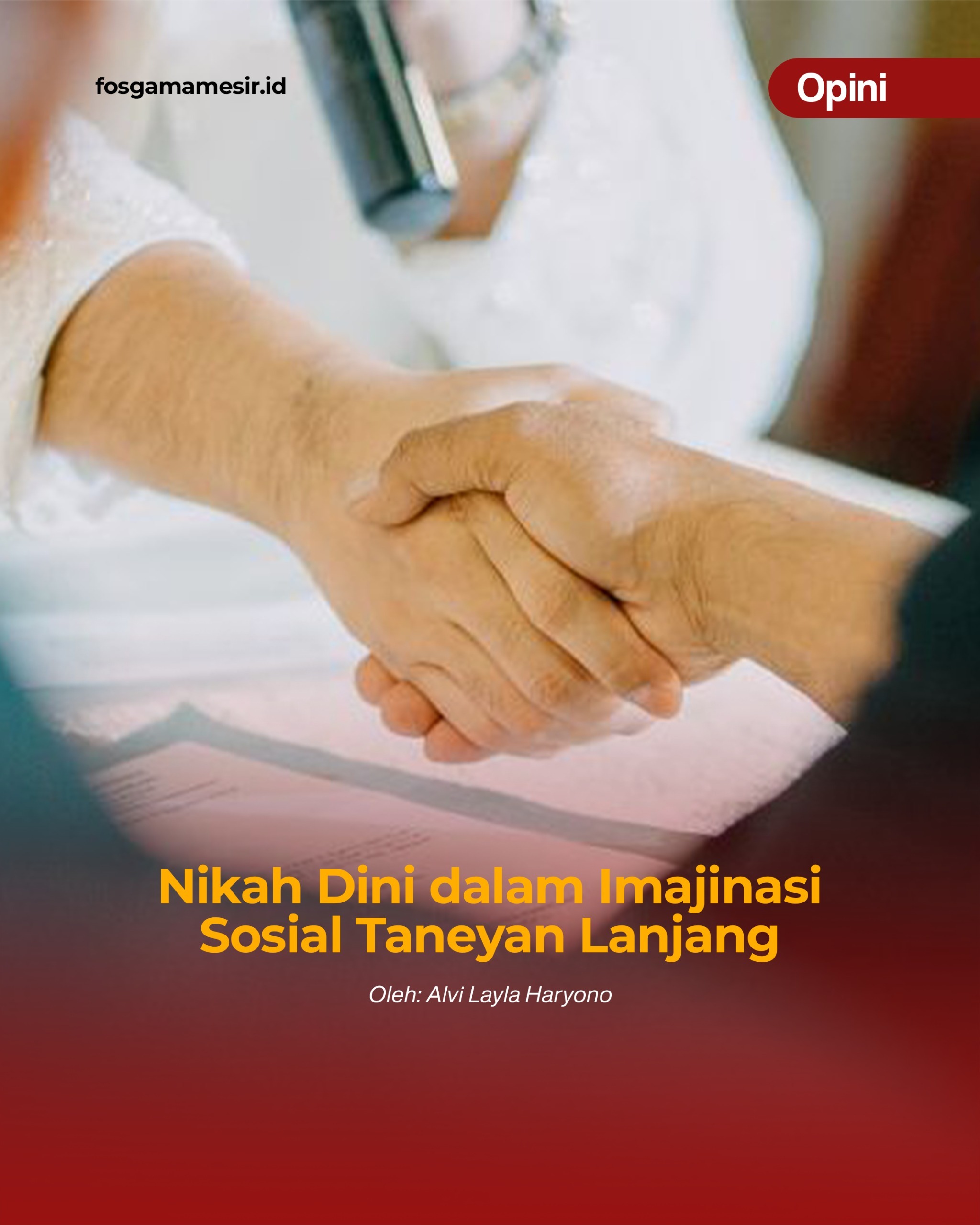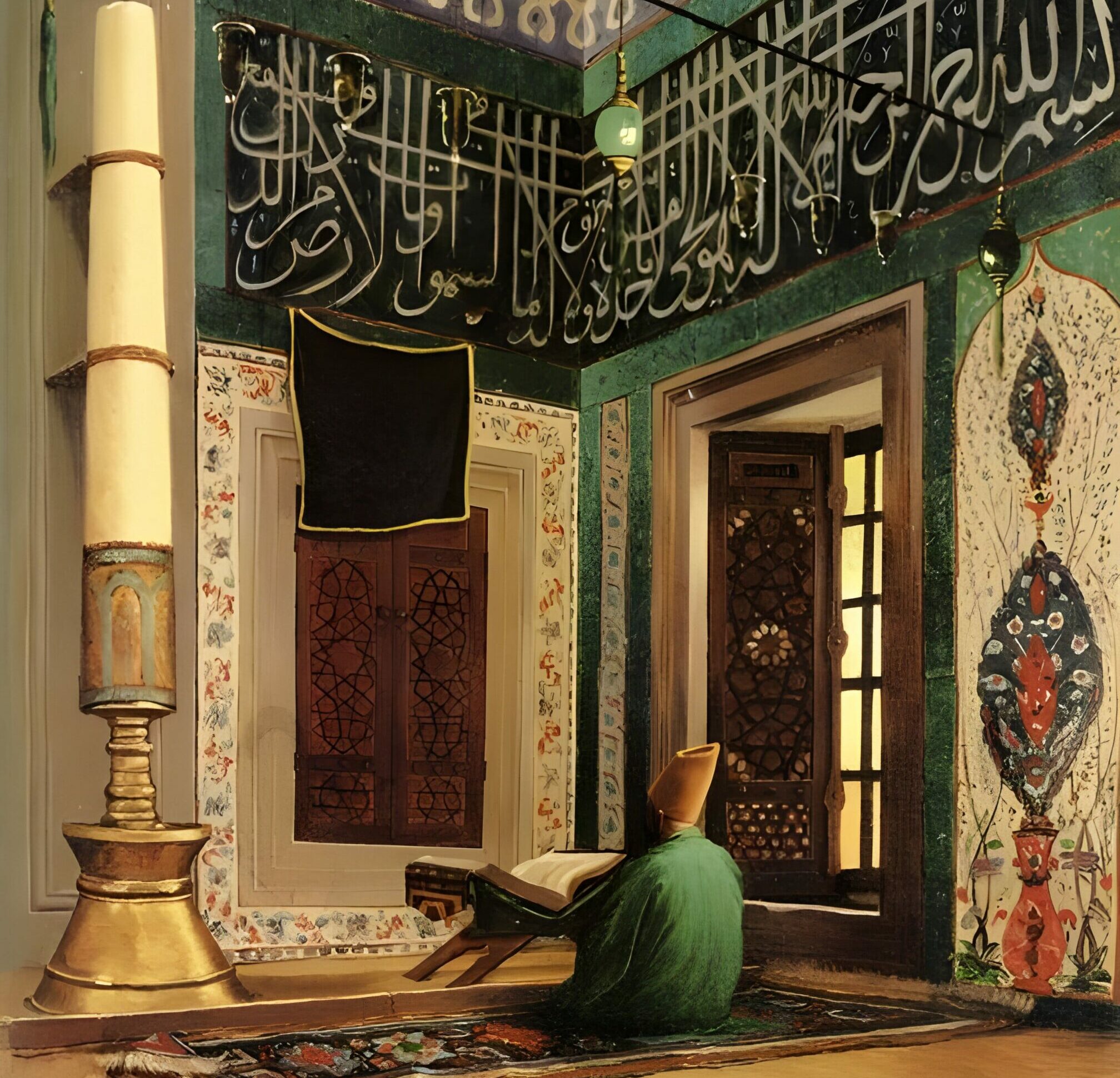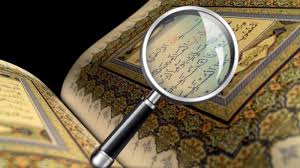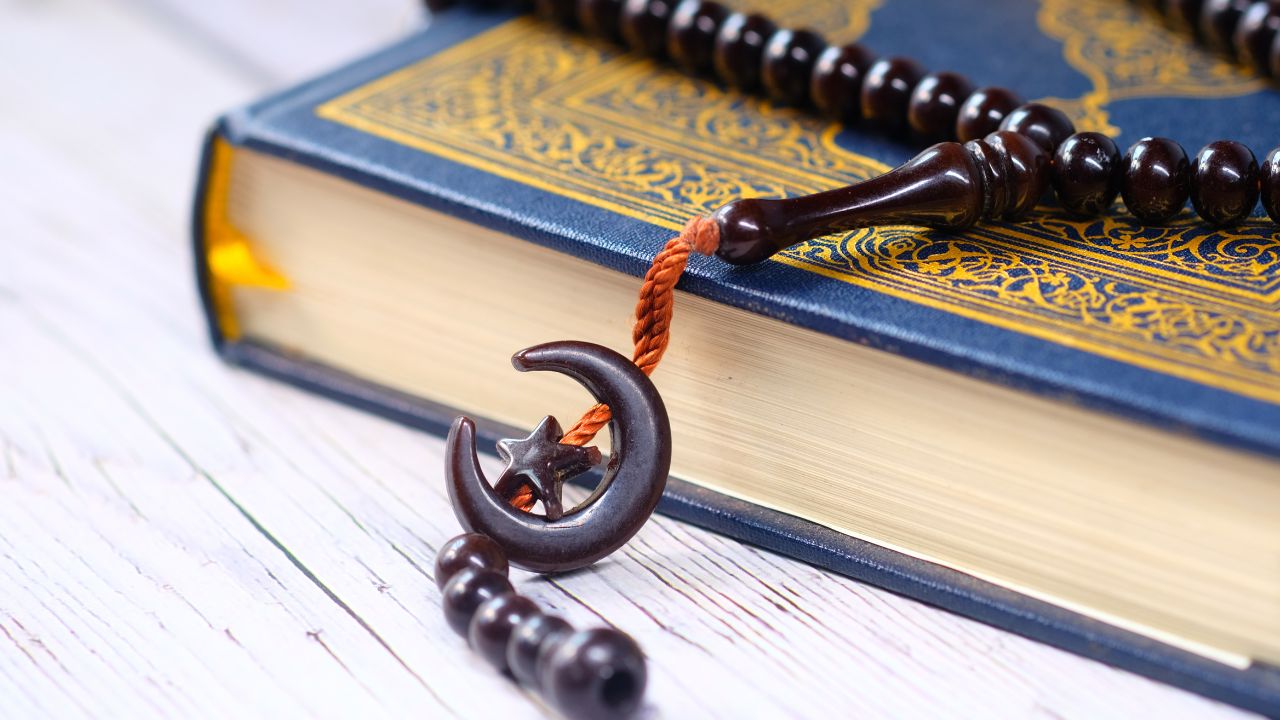Fosgama Mesir – “Saya tidak mau menikah, Buk! Saya masih kepingin wisuda!”. Teriakan teman saya, sore di penghujung 2019 itu, menggema di halaman pondok. Tangannya diseret oleh ibunya, sedang kakinya berusaha mempertahankan diri untuk tetap jejek di halaman pondok. Kami semua hanya bisa tertunduk pilu, merasai kepedihan yang merambat lewat teriakan dan tangisnya. Kami sedih melihat runtuhnya cita-cita salah satu teman kami. Kami pedih melihat wajah kalah Ibu Nyai. Ia kalah oleh desakan orang tua. Ia kalah memupuk mimpi santrinya.
Angka pernikahan dini di Madura memang terbilang cukup tinggi. Di daerah Bangkalan, tahun 2022, sebanyak 1.650 remaja telah menikah dini, sebagaimana dilansir dari data Kumparan.com. Angka ini terbilang cukup tinggi, mengingat kabupaten Bangkalan adalah kabupaten yang paling dekat dengan pulau Jawa. Harusnya ia adalah kabupaten yang paling tersentuh dengan arus modernitas, namun kita melihat bahwa bahkan modernitas pun tidak bisa mendobrak tradisi yang mengakar kuat di masyarakat Madura.
Berbicara tradisi, kita bisa membaca tradisi yang mengakar dalam suatu masyarakat dari berbagai medium. Dalam pembahasan tradisi pernikahan dini masyarakat Madura, salah satu aspek yang bisa dilacak adalah pembacaan imajinasi sosial yang terbentuk dari aktivitas merumah orang Madura, yaitu Taneyan Lanjang. Secara harfiah, ia diterjemahkan sebagai “halaman yang panjang”, dan merupakan bentuk permukiman tradisional masyarakat Madura. Ia berupa halaman yang memanjang, terdiri dari berbagai unit, yaitu langgar, rumah-rumah keluarga besar, dapur, kandang, dan terkadang pemakaman leluhur, yang semuanya mengelilingi halaman kosong di tengah.
Dalam bukunya, Menolak (di)lupa(kan): Politik Tubuh dan Kuasa Tanean dalam Bingkai Kultural Madura, Khaerul Umam Noer menganggap bahwa Taneyan Lanjang merupakan konstruksi fisik dari gambaran reflektif orang Madura dalam melihat dunia. Khaerul Umam rupanya meminjam penelitian Tulistyantoro, 2005, dalam titik pijak argumennya. Tulistyantoro, seorang dosen Jurusan Seni dan Interior Universitas Petra Kristen Surabaya, menuturkan bahwa konstruksi fisik Taneyan Lanjang tidak hanya berasaskan fungsionalitas layaknya bangunan modern, pun tidak hanya mementingkan faktor estetika dan visual belaka. Lebih dari itu, ia adalah perwujudan esensi pemikiran dan budaya masyarakat, sekaligus menyimpan nilai-nilai jati diri yang terkandung di dalamnya.
Hal ini terlihat jelas dalam penempatan unit-unit dalam Taneyan Lanjang. Langgar, tempat terbuka yang biasanya menjadi tempat menerima tamu dan tempat istirahat laki-laki, terletak di bagian ujung luar taneyan. Perempuan jarang menempati langgar, ia lebih sering menempati rumah-rumah yang berada di kompleks dalam Taneyan Lanjang. Tamu tidak boleh menempati area rumah tanpa seizin keluarga, ia hanya bisa masuk pada area langgar.
Sejatinya, penempatan langgar-rumah beserta aturan yang mengikatnya ini merujuk pada dikotomi luar-dalam Taneyan Lanjang, yang bermuara pada dikotomi penempatan laki-laki dan perempuan dalam imajinasi sosial masyarakat Madura. Langgar adalah metafora dunia laki-laki; bebas, terbuka, dan pelindung. Sedangkan, rumah adalah metafora dunia perempuan; terbatas, tertutup, dan yang terlindung. Oleh karena itu, perempuan menjadi simbol harga diri tertinggi masyarakat Madura, melebihi harta, takhta, bahkan nyawa.
Melampaui penempatan fisik unit-unit Taneyan Lanjang, kita beranjak pada mekanisme keluarga Madura dalam mempertahankan Taneyan Lanjang. Ekonomi adalah hal pertama yang harus distabilkan dalam Taneyan Lanjang. Sebagai masyarakat tegalan, mayoritas masyarakat Madura bertahan hidup dari bertani. Biasanya, di samping Taneyan Lanjang terletak tanah turun temurun yang dijadikan ladang pertanian sebagai sumber ekonomi keluarga. Tanah ini dikelola oleh seluruh anggota Taneyan Lanjang, baik ia laki-laki maupun perempuan dengan pembagian kerja masing-masing.
Pengelolaan tanah ladang Taneyan Lanjang dengan partisipasi seluruh anggotanya ini mengharuskan adanya keterikatan emosional yang kuat antar anggota Taneyan Lanjang. Ikatan emosional ini terbentuk dari interaksi-interaksi menyehari antar anggota Taneyan Lanjang. Ketua Taneyan Lanjang, yang menempati rumah induk, akan selalu berusaha sebisa mungkin untuk menjaga stabilitas kedamaian antar anggota Taneyan Lanjang.
Dari kedua hal di atas; penempatan unit fisik Taneyan Lanjang, sekaligus mekanisme pertahanan dasar Taneyan Lanjang dengan aspek ekonomi dan emosionalnya, kita bisa menguraikan akar tradisi pernikahan dini dalam masyarakat Madura. Pertama, pernikahan menjadi bentuk negosiasi masyarakat Madura dalam mempertahankan kehormatan dan harga diri perempuan, yang berarti mempertahankan kehormatan dan harga diri keluarga Taneyan Lanjang. Perempuan yang sudah menikah dianggap terbebas dari fitnah, pun terlepas dari kutukan perawan tua yang menakutkan. Hal ini sesuai dengan nilai yang terkandung dalam penempatan unit fisik Taneyan Lanjang, yaitu nilai penghormatan dan penjagaan terhadap perempuan.
Kedua, pernikahan menjadi motif untuk menarik sumber daya laki-laki ke dalam Taneyan Lanjang. Dalam tradisi masyarakat Madura, laki-laki yang sudah menikah akan pulang ke rumah istrinya. Bertambahnya laki-laki sekaligus menjadi bertambahnya sumber daya manusia yang mengelola ladang. Apalagi, anak yang terlahir dari pernikahan tersebut juga turut menjadi aset potensial untuk meregenerasi roda pergerakan ekonomi keluarga.
Ketiga, pernikahan menjadi simbol pengikat keluarga di dalam Taneyan Lanjang. Seperti yang disebutkan di muka, kepala Taneyan Lanjang akan selalu berusaha menstabilkan ikatan emosional antar anggota, maupun ikatan yang terjalin dengan keluarga Taneyan Lanjang lainnya. Motif keterikatan keluarga ini juga menjadi motif dibalik fenomena perjodohan yang marak di Madura hingga kini. Poin kedua dan ketiga menjadi manifestasi dari upaya-upaya keluarga menjaga keberlangsungan Taneyan Lanjang dari segi ekonomi.
Lalu, jika pernikahan menjadi sesuatu yang penting dengan motif khas Taneyan Lanjang di atas, termaktub pertanyaan selanjutnya, ‘mengapa ia harus dilangsungkan di usia dini?’. Narasi agama turut andil cukup besar dalam hal ini. Konsep akil balig dalam agama dijadikan sebagai landasan batas minimal seorang perempuan bisa dinikahkan. Sehingga, konsep akil balig tidak hanya menentukan perpindahan seseorang menjadi mukalaf, tapi juga menentukan kepindahannya dari ketidakpantasan menuju kepantasan dalam pernikahan. Apalagi, pemutlakan nilai agama ini didukung dengan karakter masyarakat Madura yang sangat menghormati guru agama. Faktor terakhir ini sebenarnya yang menjadi faktor kunci. Dikuatkan oleh penelitian Mardhatillah (2014), tradisi pernikahan dini lebih menguat dalam masyarakat pedesaan Madura, sebab secara kultural mereka lebih dekat dengan tokoh agama daripada masyarakat perkotaan yang mulai tersentuh modernitas.
Walakhir, meski pernikahan dini mengakar begitu kuat dalam tradisi masyarakat Madura, diseminasi akan bahaya pernikahan dini perlu terus digalakkan. Tidak banyak sosok seperti Ibu Nyai dalam paragraf pertama yang terang-terangan menolak pernikahan dini. Pengajaran dan penolakan atas pernikahan dini harus terus diinisiasi oleh mereka yang berpendidikan dan melek atas hal-hal ini. Sehingga, sedikit demi sedikit masyarakat Madura mulai perlahan meninggalkan tradisi pernikahan dini, tanpa harus mencabut akar kearifan norma masyarakat Madura.