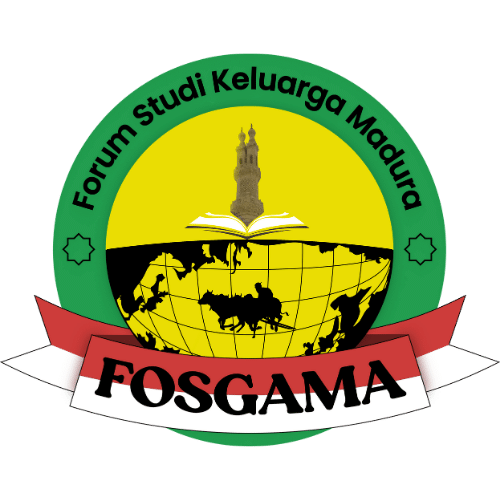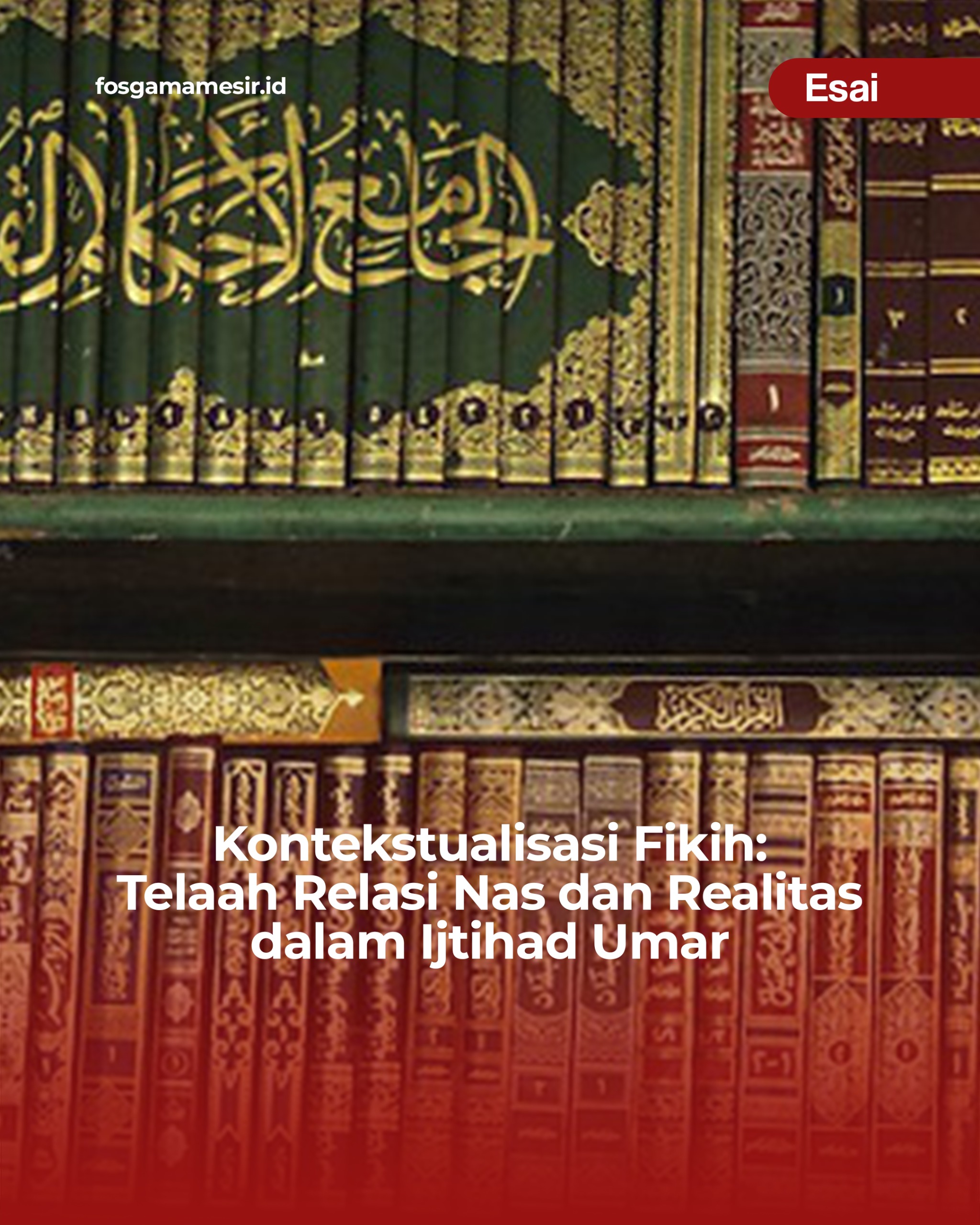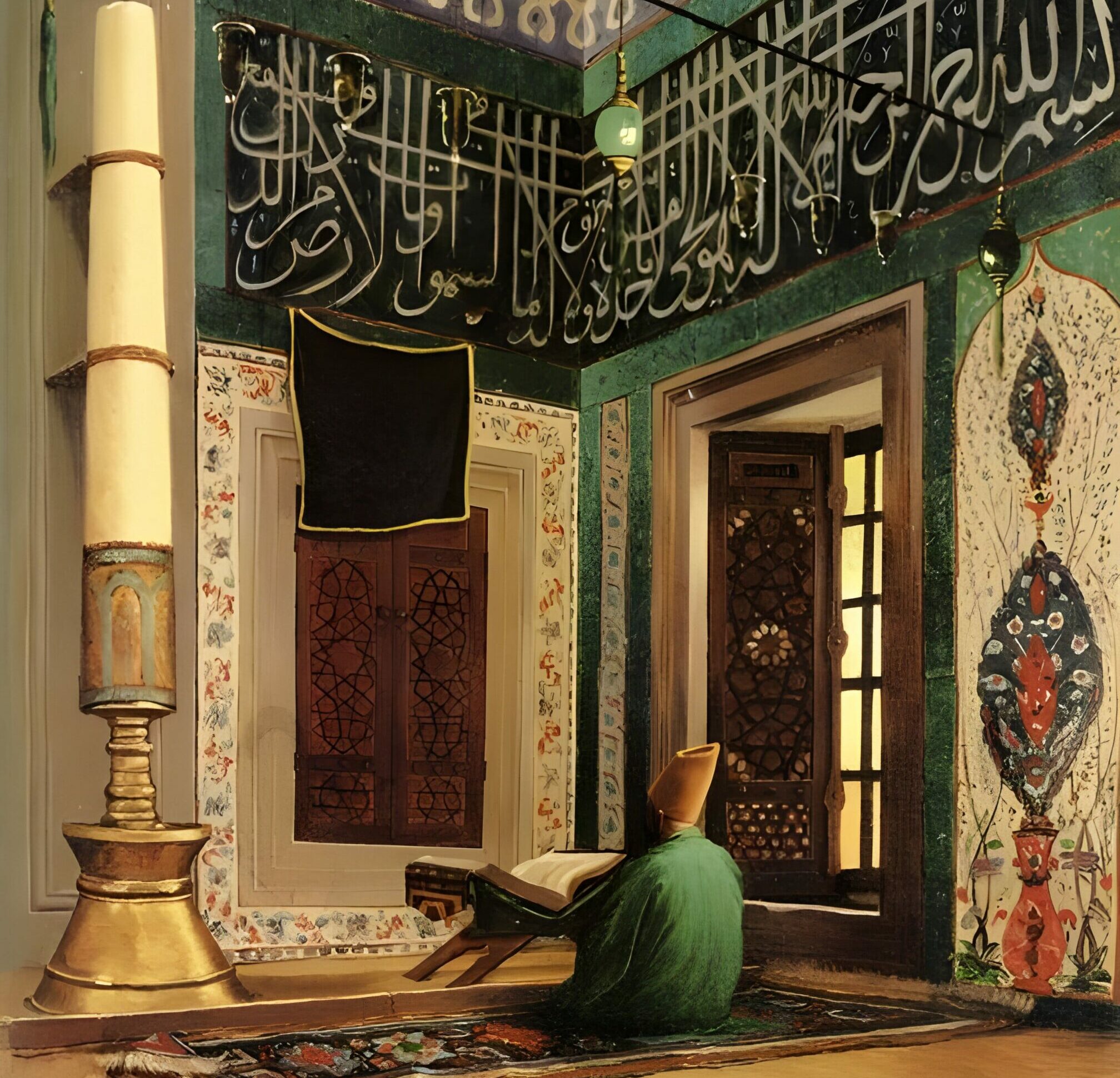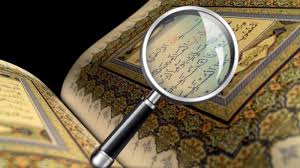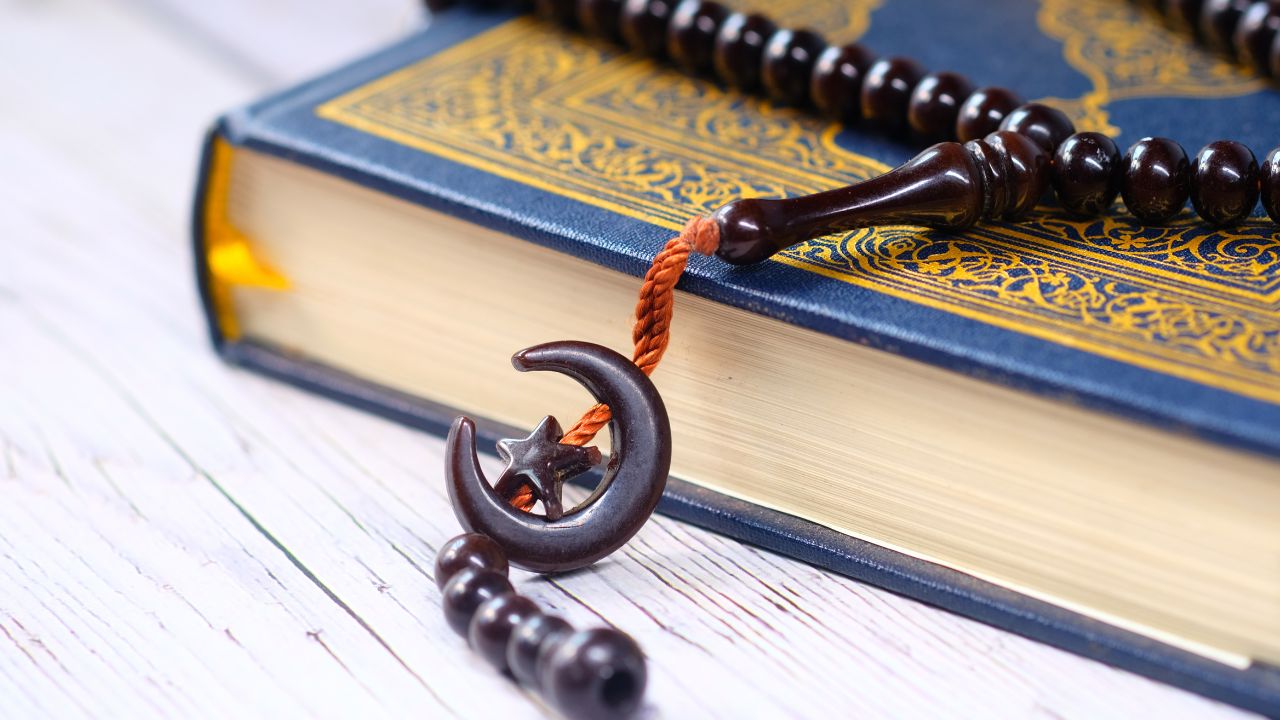Oleh : Afrozul Mukhoiyirin
Fosgama Mesir – Ilmu Fikih merupakan salah satu regulasi keilmuan Islam tradisional yang kompleks serta berorientasi mengatur segala perilaku manusia dalam pelbagai aspek kehidupan. Secara garis besar, ruang lingkup ilmu fikih adalah ketetapan syara’ terhadap perbuatan mukalaf yang menyangkut persoalan ibadah, mu’amalat (transaksi antar manusia), munakahat (pernikahan), dan jinayah. Oleh karena itu, hukum fikih selalu berdasarkan dalil. Hujah sebuah dalil harus dibuktikan dengan dalil pula. Sebab itu, pengkaji sebuah masalah dalam perspektif hukum Islam harus mengetahui rambu- rambu nalar ijtihad dan tidak boleh melampauinya. Siapapun yang bergelut dalam ilmu tersebut, dan melanggar rambu-rambu ini, sejatinya tidak mewakili sudut pandang hukum Islam, tetapi pandangan pribadi atau mengadopsi sudut pandang lain.
Diskursus fikih realitas merupakan wacana penting dalam disiplin ilmu fikih. Karena fikih tidak sebatas penggalian sebuah hukum atau memahami nas saja, melainkan juga menyangkut skema merealisasikan nilai-nilai syariat dalam realitas, maka abstainnya fikih akan realitas bisa berakibat fatal. Sebab, tujuan dari kajian realitas ini agar menjamin terwujudnya ruh atau nilai yang ingin direalisasikan dari sebuah hukum. Sehingga munculnya ijtihad maupun fatwa yang lahir dari ketidak pahaman utuh tentang syariat dapat terhindari.
Secara historis, umat Islam sepeninggal Rasulullah mengalami tantangan baru yang mendesak untuk melakukan pengembangan fikih mengingat realitas tidaklah statis. Sedangkan nas al-Qur’an dan Hadis yang menjadi sumber pokok syariat jumlahnya sangat terbatas. Faktor ini menuntut adanya jawaban hukum yang merepresentasikan ajaran Islam yang dinamis, guna mempertahankan relevansi ajaran Islam yang membawa maslahat bagi manusia di dunia dan akhirat. Mereka yang memiliki kapabilitas untuk melakukan ijtihad harus bisa menjawab tantangan ini. Namun, tantangan ini tidaklah sederhana, para sahabat harus mengelaborasi pemahahan realitas secara utuh dengan pemahaman terhadap hukum yang pantas diterapkan atas realitas tersebut. Sehingga dari dua pemahaman tersebut, akan tercapai gagasan fikih yang relevan dengan segala tuntutan zaman.
Gagasan seperti ini sejatinya telah dipraktikkan sejak masa awal Islam, terutama oleh Umar bin al-Khaththab yang menjadi pioner ijtihad maqashidi setelah Rasulullah wafat. Umar dikenal sebagai sahabat yang kerap kali mengemukakan pemikiran cerdas, kreatif dan inovatif. Bahkan, Umar merupakan sahabat yang paling memahami esensi al-Qur’an. Di antara privilese yang Allah berikan kepadanya adalah diabadikannya beberapa ayat dalam al-Qur’an dan dalam Hadis sebagai bentuk konfirmasi atas gagasan Umar, yang kemudian disebut sebagai “Muwafaqat Umar”.
Sekalipun ide kreatif dan sumbangsih Umar mengenai hukum Islam sangat banyak, komentar- komentar negatif atas gagasan ijtihadnya tidak dapat terhindarkan. Beberapa ijtihad progresifnya dianggap mengambil prinsip maslahat dan mengabaikan ketentuan konsep al-Qur’an dan Hadis. Dalam al-Jami’ li Ahkam al-Qur’an, al-Qurthubi mengemukakan beberapa kronologi turunnya ayat al-Qur’an yang bertepatan dengan pendapat Umar. Di antaranya, ayat tentang makam Ibrahim sebagai tempat salat (QS. 2:125), ayat hijab (QS. 33:53), ayat opsional cerai terhadap istri Nabi (QS. 66:5), ayat penciptaan manusia (QS. 23: 14), dan ayat tawanan Perang Badr (QS. 8: 67-68).
Seperti persoalan potong tangan pada masa paceklik, tidak membagikannya lahan pertanian di Mesir dan Irak kepada tentara Islam, hukum talak tiga dalam satu ucapan, dan banyak lagi kebijakannya ketika menjabat sebagai khalifah.
Sebelum membahas ijtihad Umar, penting kiranya untuk menyampaikan sikap Umar terhadap nas dan metodologi ijtihadnya. Umar dikenal sebagai sahabat yang sangat berpegang teguh terhadap al-Qur’an. Ia tidak akan ragu untuk merujuk pendapatnya apabila menyalahi nas. Begitu juga sikapnya terhadap Hadis, Umar sangat berhati-hati atas riwayat para sahabat. Terkadang, ia menolak beberapa riwayat yang ia nilai berseberangan dengan nas al-Qur’an atau Hadis lain. Sekalipun menurut ushuliyyin riwayat sahabat berstatus makbul, tindakan Umar dinilai salah satu bentuk verifikasi terhadapat keautentikan Hadis. Oleh karena itu, ia memiliki watak yang sangat keras kepada siapa saja yang menyalahi al-Qur’an dan Hadis.
Sekalipun Umar dinilai sangat berani melakukan ijtihad dengan mengaplikasikan metodologi musyawarah dan dialognya untuk merumuskan jawaban terhadap persoalan baru yang tidak dijumpai status hukumnya dalam nas, ia melarang tegas memutuskan hukum dengan sekadar menggunakan akal. Seperti perkataan Umar: “Berhati-hatilah kalian terhadap ashab ar-ra’yi, karena mereka adalah musuh-musuh sunnah. Mereka berat menghafal Hadis-hadis Nabi, sehingga mereka sesat dan menyesatkan.”
Salah satu contoh ijtihad progresif Umar yang kontroversial adalah tidak ditegakkannya hukuman potong tangan kepada pelaku tindak kriminal pencurian di ‘am maja’ah (tahun paceklik). Para ahli fikih sepakat tentang kewajiban hukum potong tangan apabila terpenuhi syarat-syarat qath’u. Hal itu sesuai dengan firman Allah dalam (QS. 5: 38) dan (HR Bukhari, no. 1282). Setelah masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar pernah menegakkan hukuman tersebut. Dalam Tafsir al-Qurthubi, Umar pernah memotong tangan Ibnu Samuroh ketika mencuri. Ayat had potong tangan bagi pencuri dalam surah al-Maidah qath’iyyu al-tsubut wa al-dalalah. Kandungan ayat tersebut bersifat absolut, tidak ada determinasi budaya, waktu, tempat dan kondisi. Akan tetapi, pada tahun maja’ah (peristiwa paceklik yang terjadi di tanah Hijaz pada tahun 18 hijriah akibat curah hujan yang minim terus-menerus sehingga warna tanah berubah seperti arang), Umar meniadakan hukuman tersebut.
Untuk merespon ini, penulis akan menyampaikan beberapa telaah ijtihad Umar perspektif al-Buthi dalam bukunya, Dlawabith al-Mashlahah. Menurutnya, sejatinya Umar tidak pernah membangun fatwanya atas dasar maslahat dan menyalahi al-Qur’an dan Hadis sebagai mana yang dituduhkan. Justru hal tersebut membuktikan kuatnya Umar dalam berpegang teguh dan memahami nas. Kendati demikian, hal ini tidak bisa dipahami kecuali oleh orang yang memahami prosedur dalalah nash (implikasi teks) dan metodologinya dengan kompleks. Oleh sebab itu, al-Buthi menolak pandangan al-Thufi dan tokoh muta’akhkhirin yang menganggap mashlahah merupakan sumber hukum Islam yang independen berasaskan ijtihad Umar.
Dalam perspektif Ushul Fikih, cara pandang Umar ini merupakan wujud pemahamannya yang padu terhadap nas dan realitas. Jika diklasifikasikan, pandangannya tidak hanya terbatas pada satu prinsip dan satu kaidah. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memandang ijtihad Umar sebagai praktik qiyas, dengan meng-qiyas-kan masa paceklik kepada syubhat lain yang menggugurkan had potong tangan.
Al-Dawalibi mengatakan bahwa hal ini termasuk dalam kategori perubahan hukum sebab perubahan zaman. Sedangkan al-Buthi memiliki analisis tersendiri secara detail. Menurutnya kebijakan Umar merupakan praktek identifikasi sebab-sebab diberlakukannya hukum sesuai dengan realitas yang terjadi (tahqiq al-manath) yang merupakan bagian dari visualisasi atas sebuah masalah. Ia menegaskan bahwa ayat 38 dalam al-Maidah bukan merupakan teks eksplisit, tetapi merupakan teks general yang bisa dibatasi (‘am qabilun li al-takhsish). Umar melihat bahwa ayat ini harus dikaitkan dengan teks lain yang bisa mempersempit cakupannya. Seperti Hadis Rasulullah: “Tinggalkan had sebab adanya syubhat,” Menurut Umar, pencurian yang dilakukan pada kondisi kelaparan dan paceklik termasuk syubhat yang dapat menggugurkan had.
Dari pemaparan beberapa pendapat beberapa ulama di atas, bahwa Umar mencoba menghubungkan fikihnya dengan nas. Kemudian ia menyimpulkan bahwa pencurian dalam ayat al- Maidah adalah tindakan mengambil harta orang lain secara diam-diam. Dari sinilah, Umar menerapkan pemahamannya terhadap pelaku tindak kriminal pencurian dalam ‘am maja’ah. Ia menetapkan bahwa madzinnah dlarurot menempati posisi dlarurat itu sendiri. Sehingga tidak ada keharusan untuk melakukan klarifikasi kepada pelaku kriminal pencurian pada masa itu.
Di antara praktik tahqiq al-manath (verivikasi illat)lain yang Umar terapkan dalam kebijakannya adalah pemberhentian distribusi zakat kepada mualaf. Menurutnya, pendistribusian zakat kepada mualaf adalah untuk melunakkan hati mereka. Hal inilah yang menjadi illat sebagaimana kondisi fakir dan miskin menjadi sebab seseorang menjadi mustahik zakat. Oleh sebab itu, Mualaf pada saat itu tidak lagi berhak menerima zakat karena Islam sudah mengalami kemakmuran dan kejayaan, sehingga tidak perlu menggunakan zakat untuk merebut hati mereka.
Cara pandang ini tidak kontradiksi dengan nas, tetapi merupakan penerapan metode penggalian hukum, yang merupakan salah satu tahapan ijtihad, yang disebut tahqiq al-manath. Dalam Musallam al-Tsubut, Muhibullah Ibn Abdus Syakur mengatakan bahwa pemberhentian distribusi zakat yang dilakukan oleh Umar merupakan representasi atas pemberhentian sebuah hukum sebab sudah tidak adanya illat yang melatarbelakanginya.
Selain contoh di atas, banyak ijtihad Umar yang terbangun atas dasar pemahaman teks yang komprehensif dengan berupaya menalar nas menggunakan pendekatan bayani secara kontekstual yang mencakup landasan filosofis dan sosiologis. Seperti tidak membagikannya lahan pertanian di Irak dan Mesir kepada tentara muslim, ushuliyyin mengklaim hal tersebut merupakan ijtihad Umar dengan konsep consideration of public interest (al-Maslahah al-Mursalah). Konsep ini, juga Umar terapkan dalam persoalan hukum talak tiga dalam satu ucapan.
Maka dari itu, pada dasarnya konsep maslahat bisa diterapkan sebagai alat istinbath ahkam. Dalam bukunya, al-Buthi menyatakan hukum maslahat dapat dijadikan sebagai sumber hukum jika memenuhi lima kriteria yang ia istilahkan dengan Dlawabith al-Mashlahah. Pertama, maslahah tersebut harus termasuk ke dalam ruang lingkup al-Maqashid al-Syar’iyyah yang lima. Kedua, tidak bertentangan dengan al-Qur’an. Ketiga, tidak bertentangan dengan Hadis. Keempat, tidak bertentangan dengan qiyas. Kelima, tidak bertentangan dengan maslahat lain yang lebih tinggi, lebih kuat, atau lebih urgen.
Meskipun secara zahir, ijtihadnya mengandung maslahat, tetapi bukan maslahat tersebut yang meletarbelakangi ijtihad-ijtihad progresifnya. Sebagai seorang khalifah, tentunya ia memahami kondisi sosial, politik, dan ekonomi umat islam pada saat itu. Sehingga tidak ayal apabila ijtihadnya terkadang terkesan mengesampingkan nas. Hal inilah yang pada akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya fikih metodologis (madzhab manhaji).
Potret singkat kontekstualisasi fikih realitas di atas, kiranya cukup menjadi acuan para pengkaji ilmu fikih untuk memahami fikih secara kompleks. Umar bin al-Khaththab merupakan sahabat yang paling banyak menerapkan konsep maqashid syariah dalam ijtihad progresifnya. Kontekstualisasi fikih yang Umar terapkan dengan menganalisa terhadap maqashid sekaligus menginterpretasi ulang teks untuk menjawab konteks baru merupakan salah satu konsep mewujudkan cita-cita Islam yang ideal dan dinamis. Jadi, mengingat fikih lahir proses ijtihad manusia, maka fikih bisa berkembang dan diperbaharui selama tidak menyalahi rambu-rambu yang telah ditetapkan.
Said Aqil Siroj menegaskan tentang urgensi memahami realitas agar tidak kaku dalam memahami fikih: “Kontekstual dalam berfikih bukan berarti menanggalkan pendapat fukaha (pakar fikih) secara keseluruhan, tetapi memahami fikih Islam sesuai dengan ruang dan waktunya dengan metode yang sudah diletakkan fukaha. Menganggap suatu pendapat fikih sebagai kebenaran permanen untuk segala kondisi justru membawa degradasi umat Islam dalam berinterakasi dengan perkembangan zaman. Dalam hal ini, fukaha klasik sendiri pada dasarnya sering memperingatkan agar tidak kaku dalam memahami fikih.”
Menurutnya, pola pikir jumud (hanya bermodalkan teks-teks ulama) telah mengeluarkan fikih dari tabiatnya sebagai ilmu praktis yang bersentuhan dengan amaliah manusia. Logikanya adalah Ketika perilaku manusia bisa berubah sesuai ruang dan waktu, maka fikih juga menerima perubahan agar tetap sesuai dengan ruang dan waktu.
Al-Qarafi mengatakan, “Apabila tradisi mengalami pembaharuan, maka pertimbangkanlah. Apabila tradisi tersebut sudah tidak berlaku, maka tinggalkanlah. Janganlah kamu terpaku pada apa yang tertuang dalam kitab ulama. Akan tetapi, jika seseorang dari daerah lain datang kepadamu meminta fatwa, maka jangan berlakukan baginya tradisi daerahmu. Akan tetapi tanyakan tradisi di daerahnya dan berfatwalah sesuai dengan kondisi tradisi daerahnya, bukan tradisi dan ketetapan teks ulama daerahmu. Ini adalah metode yang benar. Berperilaku jumud atas teks ulama adalah bentuk kesesatan dalam agama dan ketidaktahuan atas tujuan ulama Islam dan salaf salih.”
Poin yang menjadi persoalan disini adalah sulitnya menyelami sebuah realitas agar selaras dengan maqashid syariat (ijtihad maqashidi). Lalu bagaimana kita bisa memahami sebuah realitas? Abdullah bin Bayyah memandang pentingnya memahami sebuah realitas dengan konsep tahqiq al-manath (verification of cause). Demikian pula, al-Ghazali mengemukakan lima komponen pokok untuk memahami sebuah realitas mulai bahasa, kultur, indra, nalar, hingga watak. Lima komponen ini dikenal sebagai standardisasi tahqiq. Ibn Bayyah juga menyatakan bahwa tahqiq al-manath merupakan salah bentuk ijtihad yang dapat diterapkan sepanjang zaman. Berbeda dengan dua saudaranya, takhrij al-manath (specification of cause) dan tanqih al-manath (refining of cause). Keduanya terputus seiring meninggalnya ulama yang mencapai level mujtahid mutlak.
Walakhir, merupakan sesuatu yang natural jika kajian fikih lebih digaungkan dengan mendudukkan dan mendialogkan relasi antara teks dan realitas. Terlebih di era kiwari yang ini. Pemahaman kitab kuning dengan bermodalkan melihat kertas tanpa mempertimbangkan kondisi individu, sosial, dan faktor-faktor lain, atau bahkan lebih mendahulukan daya nalar dan mengesampingkan nas dapat mendorong untuk melakukan tindakan anarkis atas nama agama. Sikap inilah yang pada akhirnya mengaburkan tujuan utama dari agama itu sendiri. Tidaklah berlebihan, jika penulis menganggap pelestarian fikih realitas merupakan “civilational imperative” (keharusan peradaban). Mengingat ilmu fikih merupakan warisan intelektual peradaban Islam klasik.