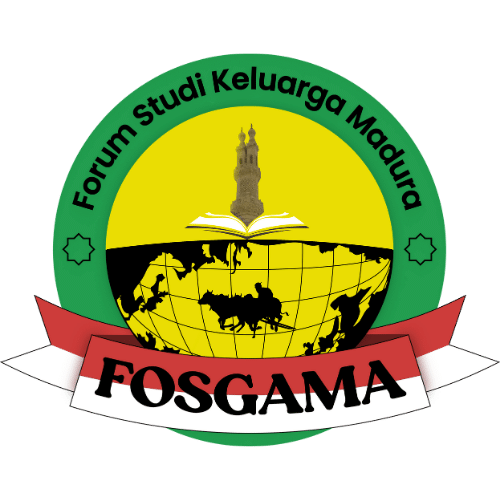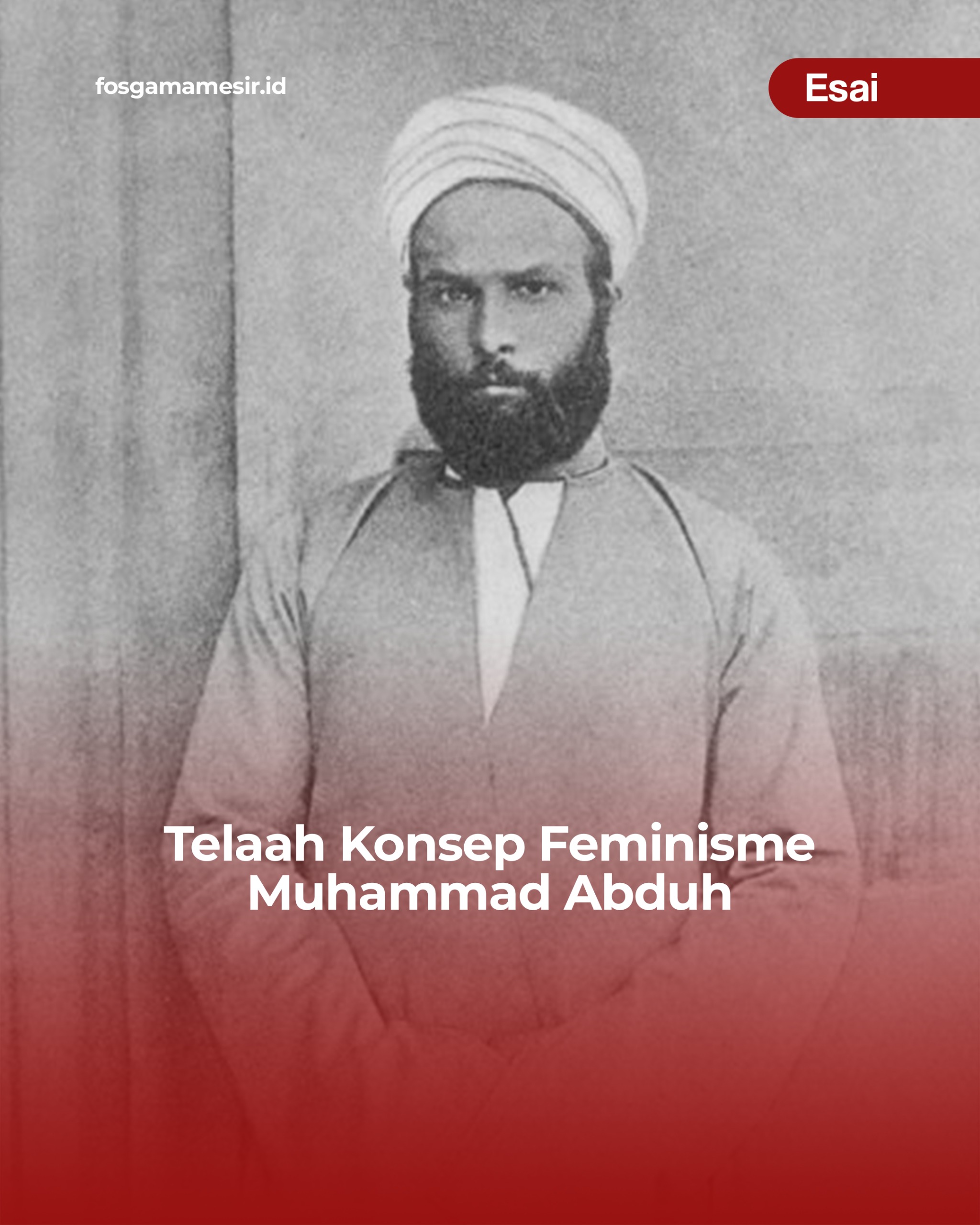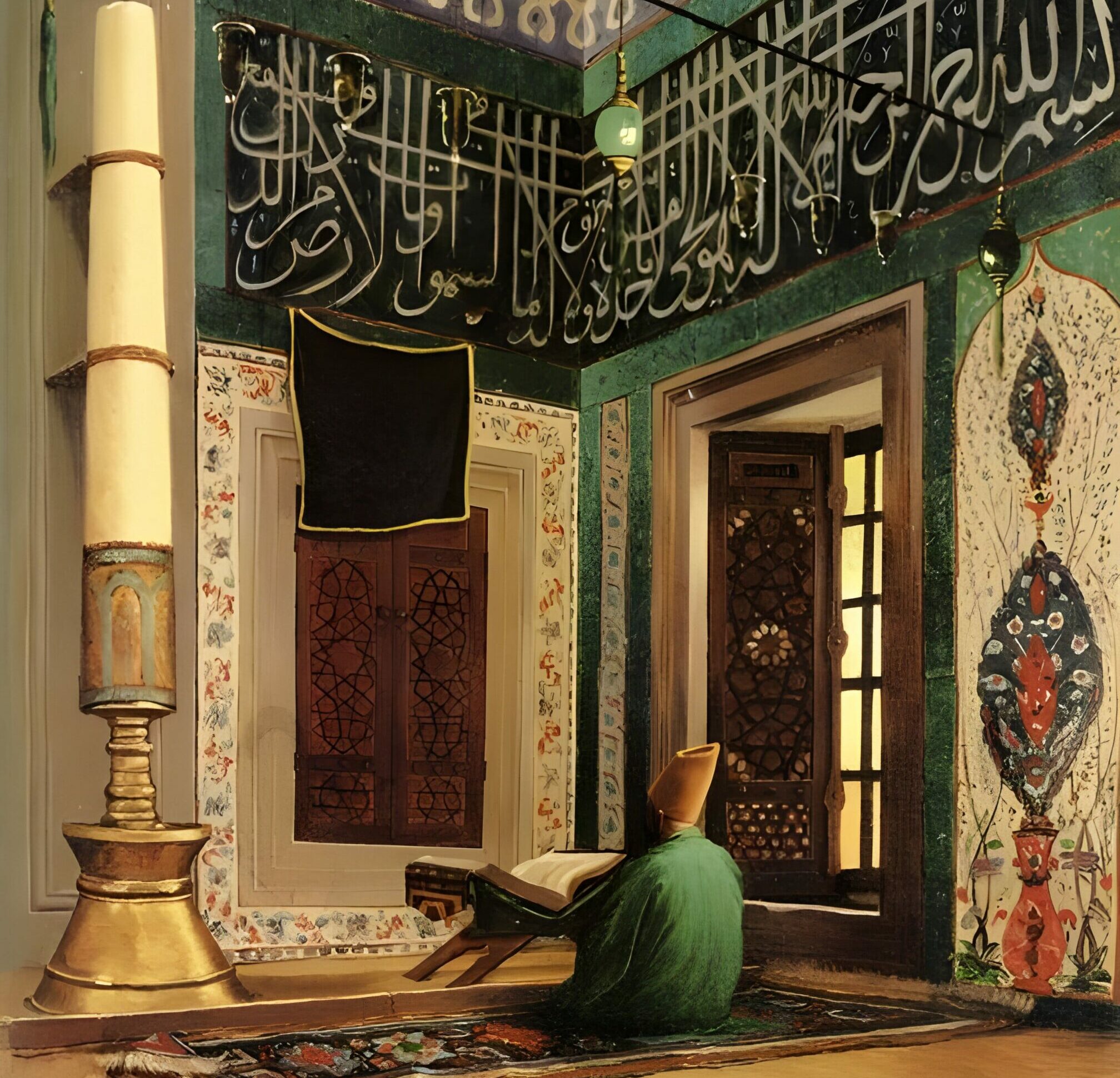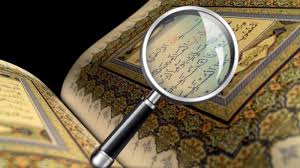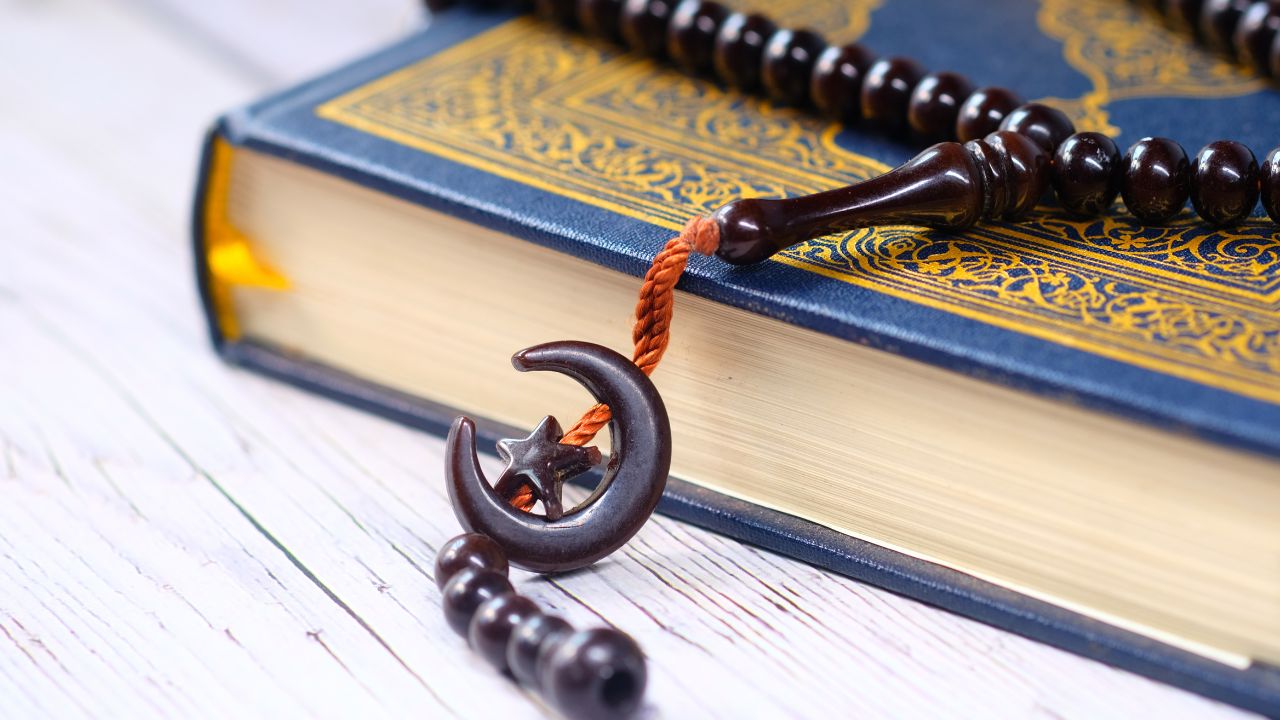Oleh: Abdussalam Misluky
Fosgama Mesir – Isu kesetaraan gender adalah topik yang sangat menarik untuk terus diulas di era kontemporer. Ia melebur dalam gerakan perjuangan yang dipelopori oleh kaum hawa untuk memperoleh kesetaraan hak, sebagaimana laki-laki, dalam berbagai aspek: politik, hukum, sosial dan lain sebagainya. Seiring berkembangnya zaman gerakan ini populer dengan istilah feminisme. Ia dilatarbelakangi oleh kesadaran moral kaum perempuan yang tersubordinasi oleh laki-laki. Bahkan, di era tertentu, wanita adalah komoditi yang bisa diperjual-belikan secara bebas.
Islam sendiri sebenarnya memberikan hak yang setara bagi wanita dan pria. Islam hanya membedakan keduanya dalam peran sosial dan hukum. Banyak kalangan cendekiawan muslim memproklamirkan hal ini. Di Mesir sendiri, Rifa’ah al-Tahtawi (wafat 1873 M.) adalah orang yang pertama kali menginisiasi isu kesetaraan gender dan kemudian dikembangkan oleh al-Imam M. Abduh.
Di antara faktor yang mendorong al-Imam untuk berkontribusi dalam isu-isu yang berkaitan dengan wanita tidak terlepas dari kondisi-kondisi sosial, ekonomi, dan politik di era beliau berada. Kondisi tersebut mendorong al-Imam untuk membangun konsep pemikiran Islami revolusioner yang dibangun di atas fondasi syariat yang berbarengan dengan ajakan untuk membuka pintu ijtihad dalam menghadirkan solusi bagi problematika masyarakat di segala lini, termasuk problematika kesetaraan gender.
Dalam pandangan beliau, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hak dan kewajiban, keduanya sama-sama berhak menjadi aktor dalam segala aspek, baik pendidikan, politik, ekonomi, dan lain lain. Penekanan beliau di sini tentang poin makna setara adalah ontologi kalimat setara itu sendiri atau hakikat maknanya. Dari sini, kita bisa sedikit mengetahui arah dari kesetaraan gender yang beliau coba terapkan di ranah sosial masyarakat.
Pandangan Abduh mengenai kesetaraan gender terpancar dalam kritikan yang belau layangkan terhadap produk tafsir yang sudah ada, di mana para mufasir terlena dengan dunianya masing-masing, sehingga mereka terjebak pada persoalan parsial. Contoh seorang ahli bahasa hanya mengarahkan perhatiannya pada bahasa al-Qur’an, seorang fakih hanya fokus pada kajian hukum, dan seorang teolog sibuk mencari legitimasi pendapatnya. Keadaan semacam ini menyebabkan pesan al-Qur’an tidak sampai secara utuh kepada umat.
Menurutnya, ketidakmampuan umat dalam menganalisis maslahat secara maksimal melahirkan anggapan bahwa wanita tidak memiliki peran apapun dalam membangun peradaban sosial masyarakat. Di sisi lain, terbatasnya kapabilitas seseorang dalam memahami dan mengimplementasikan kandungan nas secara utuh menjadi faktor utama yang menyebabkan pesan nas tidak tersampaikan secara utuh. Jadi, tidak heran umat seakan-akan kembali pada era jahiliah dalam memperlakukan perempuan.
Kejumudan dalam berpikir juga berimpak pada kaburnya pemahaman yang sahih akan syariat Islam, sehingga produk yang dihasilkan ibarat macan yang menerkam kemerdekaan para wanita dalam kehidupan sosial mereka. Dalam artian, kaum perempuan hanya sebatas mesin yang berguna sebagai asisten yang membantu kehidupan sehari-hari kaum pria. Ranah inilah yang menjadi titik fokus al-imam untuk mengingatkan kelalaian kaum muslimin selama beberapa periode lamanya.
Di samping itu, metodologi al-Imam dalam berkontribusi terhadap isu-isu wanita tidak terlepas dari metodologi-metodologi lainnya yang beliau usung selaku inisiator gerakan pembaharuan Islam. Beliau mewanti-wanti umat untuk tidak fanatik terhadap tren masyarakat Barat, walaupun di kala itu Barat merupakan peradaban maju. Sebagaimana himbauan yang beliau suarakan dalam artikelnya, khata’ al-iqala’, yang berisi tentang ajakan anti fanatisme dalam bertaklid tanpa memastikan keabsahan pendapat-pendapat yang diikuti.
Penekanan konsep kesetaraan gender versi al-Imam berporos pada roda moderat yang menjadi konsep dan tiang al-Azhar sampai sekarang. Beliau tidak anti terhadap Barat, juga tidak melantangkan gerakan westernisasi. Akan tetapi, pola yang beliau usung adalah keseimbangan dalam meniru kemajuan barat dengan catatan menjaga aturan syariat dalam pengejewantahannya.
Rumus-rumus Imam M. Abduh banyak terinspirasi dari Jamaluddin al-Afghani yang berisi tentang pesan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat timur. Kemudian beliau mengolaborasikannya dengan konsep Rifa’ah al-Tahtawi yang berpendapat bahwa pembebasan wanita dari belenggu-belenggu sesat yang mengatasnamakan agama akan terealisasi melalui pendidikan. Akhirnya, dari sinilah gagasan sosial progresif mengenai kesetaraan gender versi al-Imam lahir.
Pemahaman kesetaraan yang diusung oleh al-Imam dibangun di atas konsep kesatuan manusia universal antara laki laki dan perempuan. Entitas, akal, dan perasaan keduanya setara, berhak menyukai yang mereka senangi dan membenci apa yang tidak disenangi. Perempuan adalah entitas yang berdiri sendiri, tidak mengekor pada laki-laki kecuali dalam ranah yang ditentukan oleh syariat. Mereka bukan alat dan budak yang bebas diperlakukan secara serampangan dan tidak manusiawi.
Ranah rumah tangga juga tidak luput dari perhatian Imam M. Abduh. Sebagai pembaharu sosial, beliau berpandangan bahwa bangsa yang kuat adalah representasi dari koloni-koloni kecil yang kuat pula, yang mana koloni inilah yang akan menjadi fondasi dari suatu bangsa. Koloni yang dimaksud adalah bahtera rumah tangga yang menjadi tiang-tiang dari sebuah kelompok masyarakat. Ketika kesejahteraan dalam ruang lingkup parsial semacam ini tidak terealisasi, maka bisa dipastikan masa depan suatu bangsa akan menghadapi ancaman serius.
Berdasarkan pandangan di atas, al-Imam berusaha untuk menginisiasi terciptanya kedamaian dan terpadunya irama antara suami dan istri dengan pendapat-pendapatnya mengenai kesetaraan peran antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga yang kondusif dan seirama. Dalam artian hubungan di antara keduanya adalah hubungan horizontal bukan vertikal. Keduanya saling melengkapi satu sama lain dan merupakan entitas yang tidak terpisahkan.
Al-Imam secara gamblang mengkritik definisi pernikahan yang dirumuskan oleh sebagian ulama fikih. Definisi tersebut menyebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang membuat seorang laki-laki memiliki hak-hak tertentu atas istrinya. Menurut beliau, definisi tersebut terlalu monoton pada kepuasan jasmani saja, tanpa singgungan misi dan etika yang harus diterapkan dalam kehidupan berumah tangga. Al-Quran telah mengisyaratkan pembahasan pernikahan yang sesuai dan cocok untuk dijadikan definisi dibandingkan definisi itu. Hal ini termuat dalam surat al-Rum ayat 21 yang berisi tentang aspek pokok di dalam pernikahan, yaitu sakinah, mawadah, warahmah.
Meski kritikan beliau terkesan tajam, tapi sebenarnya beliau tidak menyalahkan definisi fikih tersebut. Hanya saja, beliau menyoroti dimensi nas dan nilai-nilai kemanusiaan yang luput dari cakupannya, mengingat definisi yang disampaikan ulama fikih sudah sesuai dengan rumus-rumus yang ada di ilmu logika (mantik). Sementara definisi ala beliau —menurut hemat penulis, masih perlu dikaji dan dijelaskan secara detail sesuai logika bangunan definisi.
Dalam merumuskan konsep kesetaraan dalam ruang lingkup rumah tangga, al-Imam menerapkan pendekatan pandangan baru terhadap nas yang bermuatan peran muslimat dalam kehidupan rumah tangga. Tidak hanya itu, dalam tafsirnya, beliau berupaya menerapkan ayat-ayat al-Quran terkait tatanan sosial rumah tangga dan perempuan dengan merumuskannya ke dalam pasal-pasal hukum. Hal inilah yang menjadi pembeda antara beliau dan pembaharu sosial serta para mufasir lainnya yang juga tertarik dengan isu-isu wanita. Dari sini kita bisa menarik benang merah tentang kesungguhan al-Imam, serta kejeniusannya dalam menghadirkan solusi yang aplikatif untuk mengatasi problematika yang ada di tengah masyarakat.
Selain itu, keistimewaan pemikiran Imam Muhammad Abduh adalah penerapan kaidah- kaidah fikih dalam menjawab problematika yang ada. Meskipun beliau bermazhab Hanafi, beliau tidak enggan menggunakan mazhab Maliki dalam beberapa fatwanya. Tentunya hal ini bukanlah suatu hal baru bagi seorang mufti seperti beliau.
Secara ringkas, fatwa-fatwa al-Imam yang berkaitan dengan peran perempuan dan bahtera rumah tangga adalah manifestasi dari penerapan konsep kesetaraan gender yang beliau usung. Hal itu bisa kita temukan dan analisis dalam fatwa beliau mengenai beberapa kasus, seperti konsep talak, poligami, serta kebebasan wanita dalam memilih pasangan.
Dari semua penjabaran di atas, kita bisa menyimpulkan satu hal yaitu betapa luar biasanya sosok al-Imam M. Abduh dalam gerakan pembaharuannya. Terutama kesigapan beliau dalam menanggapi isu-isu faktual dan aktual, seperti kesetaraan gender yang sampai sekarang pun masih menjadi perdebatan yang belum usai. Setelah wafat, perjuangan beliau dalam membela hak wanita serta teori-teorinya yang berupa tulisan atau ucapan dikembangkan dan diteruskan oleh anak-anak ideologinya seperti Rasyid Ridla, Qasim Amin, dan lain sebagainya. Beliau memang sudah wafat, akan tetapi khazanah keilmuannya selalu hidup bersama kita.